NAMAKU Karenina. Sebuah nama yang ayah curi dari perempuan yang pernah sangat ia cintai dulu. Ibu baru mengetahui asal-usul ini sekitar dua tahun yang lalu. Sifatku yang cenderung usil dan kekanak-kanakan adalah biang keladi mengapa rahasia itu meleleh.
Suatu pagi seperti biasa, ayah bersiul-siul sendiri di depan rumah sambil bercengkerama dengan ayam jago kesayangannya. Mereka selalu berdiskusi. Bahkan mimik ayah jauh lebih serius ketika berbicara dengan si jago daripada dengan kami keluarganya. Waktu itu aku terbangun pukul setengah delapan. Sudah bisa ditebak, tak mungkin lagi diterima oleh penjaga pintu gerbang sekolah yang cukup ketat peraturannya. Sambil jongkok di bawah pohon jambu aku menggodanya.
“Yah, kok kasih aku nama Karenina sih. Bukannya Angelina, Monica, Natalia, atau apa kek yang gaulan sedikit”
“Nama kamu bagus tahu! beruntung tidak ayah kasih nama Saiful atau Syamsudin”
“Tapi teman-teman lebih suka memanggilku Nina, bukan Karen seperti yang ayah dan ibu panggil”
“Nina juga bagus”
“Bagusnya di mana ?”
“Dulu ayah sering mencium jidatnya dan bilang, aku sayang kamu Nina”
“Siapa Yah, ayah kan tak pernah melakukan itu padaku?!”
Saat itu untuk pertama kalinya aku mendapati ayah tersipu malu. Serupa detektif yang haus informasi aku memaksa ayah menjelaskan siapa Nina yang ia maksud. Akhirnya ayah menutup penuturannya dengan kalimat, “jangan sampai ibu kamu tahu!”
Banyak teman-teman bilang kalau aku sangat cerewet, keranjingan mementalkan kata-kata tanpa mempedulikan batasan-batasan ataupun perasaan orang lain. Karakter buruk itu semakin terbukti ketika aku dengan gamblangnya membeberkan curahan hati ayah pagi itu pada ibu. Syukurlah reaksi ibu jauh dari kesan kecewa, dan di luar dugaan ia malah tersenyum sendiri. Usut punya usut akhirnya aku bisa paham mengapa ibu hanya tersenyum juga. Rupanya Nelly, adik lelakiku satu-satunya, namanya juga ia curi dari mantan kekasihnya dulu. Jadilah kami berdua pelampiasan kasih tak sampai mereka di masa muda.
Enam bulan lalu aku menanggalkan seragam putih abu-abuku untuk selama-lamanya. Meski berat, harus kuterima kenyataan berpisah dengan teman-teman yang begitu aku cintai. Aku memeluk mereka satu-persatu sambil menumpahkan air kesedihan layaknya adegan perpisahan Rangga dan Cinta pada ending romantis kisah “AADC” yang masyhur itu. Banyak yang tak tahu, kalau aku adalah orang yang paling sensitif di dunia ini. Mereka hanya melihat sisi luarku saja yang cenderung asal dan urakan. Mungkin satu hal yang betul-betul kuketahui tentang diriku adalah kenyataan bahwa aku tak pernah bisa membenci orang lain. Kalaupun itu sampai kulakukan, pasti tak akan berlangsung lama. Pernah terpikir kalau aku lebih menghiraukan orang-orang di sekitar, daripada mengurus diri sendiri. Hingga kini belum kumengerti apakah itu sebuah kelebihan atau kekurangan yang melekat pada diriku.
Ibu menyarankan agar aku memperdalam bahasa asing di sebuah universitas di luar kota kami. Walau sebenarnya aku ingin sekolah psikologi. Mempelajari bermacam-macam karakter manusia yang bagiku sangat menantang dan mengasyikan. Sayangnya di kota kami belum ada lembaga pendidikan yang mengajarkan bidang itu. Karena tak ada yang lebih mulia selain mengikuti keinginan orang tua, serta beberapa pertimbangan lain yang menurutku masuk akal, kuputuskan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di Fakultas Bahasa Universitas negeri terfavorit yang ibu maksud.
Mulut yang enggan berhenti meracau tidak selalu mendatangkan malapetaka. Di lain sisi bakat alami yang satu ini ternyata menjadi nilai tambah bagiku. Aku lebih mudah akrab dengan lingkungan baru daripada teman-teman yang lain. Dalam kurun yang tidak begitu lama, hampir semua senior di kampus menjadi sahabat karibku.
Umurku delapan belas tahun. Untuk seorang perempuan, berarti aku sedang berada pada titik di mana kebahagiaan belum menampakkan definisinya secara pasti. Dan cenderung menganggap laki-laki sebagai mahluk yang lebih pantas dipuja ketimbang diwaspadai. Lazimnya seorang mahasiswa baru, serupa mereka yang lain, aku mengagumi beberapa kakak tingkat yang menarik hati. Simpatiku yang pertama tertambat pada seorang “kakak” bernama Willie. Menurutku ia sosok pria dewasa yang mampu membimbingku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Selain itu orangnya baik, sosok yang tepat untuk dimintai nasehat-nasehat. Waktu ospek, ada sebuah tradisi kirim-kiriman surat cinta dari junior kepada senior yang dirasa memikat hati. Tentulah catatan klasik itu aku layangkan untuk kak Willie tersayang.
Dari gelagatnya bisa kutangkap kalau ia juga menyukaiku. Kami sering jalan-jalan bersama, menghabiskan waktu-waktu kosong selesai jam kuliah, memadu kasih layaknya cerita-cerita remaja yang tengah ngetrend di televisi.
Tapi romantisme picisan itu tak berlangsung lama. Ternyata ia tak semerdu yang didengungkan, tak semanis yang diceritakan, rasa simpatiku mendadak memudar setelah peristiwa siang itu.
Kantin tak lagi bising oleh bibir-bibir yang gemar bergosip. Karena hari Jumat, suasana kampus menjelma sepi secara prematur. Di atas meja kecil yang membelah jarak kami, terhidang dua kaleng minuman ringan. Willie tampak menikmati batang demi batang rokok yang setahuku, adalah merek yang biasa dikonsumsi para pekerja bangunan atau orang-orang tua. Kami hanya membicarakan hal-hal sepele yang tak penting. Tentang tayangan TV favorit, warna pakaian dalam kesukaan, sampai binatang peliharaan di rumah masing-masing.
Sehabis menyeruput bagian terakhir minuman itu, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Willie melayangkan bibirnya tepat ke permukaan daun bibirku. Yang membuatku kaget, kejadian itu berlangsung begitu cepat. Jelas peristiwa ini membuatku Shock. Aku tak kuasa berbuat apapun. Dan secara alamiah meladeni saja serangan berkecepatan tinggi tadi. Toh aku juga menyukai dia. Pikirku kemudian. Sebetulnya aku tak asing lagi berciuman dengan laki-laki. Ritual percintaan ini telah beberapa kali ku praktekkan dengan mantan-mantan pacarku semasa SMA dulu. Hanya kali ini memang beda. Dari segi cara, maupun pendekatan awalnya. Tak ada acara rayu-rayuan yang telah berlaku secara konvensional di antara semua laki-laki pencinta di dunia ini.
Malamnya aku tak bisa tidur. Coba-coba menganalisa maksud Willie yang sebenarnya dari insiden tadi. Apakah ia betul-betul melakukannya dengan landasan kasih sayang, atau barangkali sekadar sebuah permainan, mungkin juga adalah tindakan pelecehan. Sel-sel pekerja di dalam otakku tak henti mengadakan penelitian. Hingga mentari meninggi, kedua indera penglihatku tak jua terkatup. Sementara jadwal kuliah pagi siap menusuk dari belakang.
Tak ada cara lain, aku harus membicarakan masalah ini secara serius dengannya. Jalan keluar satu-satunya yaitu mengkonfirmasi secara langsung kepada si pelaku. Dengan sekujur tubuh yang letih aku memaksakan diri untuk tetap kuliah hari ini. Bukan gara-gara dorongan menuntut ilmu setinggi langit, tapi karena rasa penasaran yang terus membuntuti.
Di dalam angkutan umum aku tak kuasa menahan kantuk. Kebetulan jarak rumahku menuju kampus setara dengan pergerakkan jam selama empat puluh lima menit. Durasi yang lumayan untuk diisi dengan tidur.
Di dalam kelas virus keletihan tadi terus menggerogoti dengan kejamnya. Sudah bisa kuperkirakan sebelumnya. Maka kuputuskan duduk di pojok paling kiri kursi baris belakang. Kuminta Yudiet segera membangunkanku begitu jam belajar usai.
Dan rasa letih itu akhirnya berpindah menjadi rasa geram. Aku mencarinya di tempat biasa ia dan teman-teman sekonconya nongkrong sambil memperbincangkan obrolan laki-laki. Tempat itu tak begitu jauh dari kantin utama kami. Menurutku ia telah melihatku ketika dengan sengaja aku melewati area nongkrong mereka. Sebagai perempuan, menunjukkan gengsi kadang terasa penting bagiku. Biasanya laki-laki lebih menghargai perempuan yang menjaga gengsi. Sebab itu aku tak ingin menyapanya terlebih dahulu. Di luar predikisi, ia juga melakukan hal yang sama. Willie yang kubanggakan beberapa waktu lalu seperti ditelan bumi. Ia menghindar sesudah merenggut rasa sayangku. Minggat sehabis mencicipi manis bibirku. Kini kesan yang bisa ku ingat darinya hanyalah potongan-potongan pahit yang menghasut rasa dendamku.
Ah, sudahlah. Barangkali ini peringatan keras bahwa beberapa dari sekian banyak orang memang menyebalkan. Percuma memikirkan masalah tak berguna itu berlarut-larut. Aku mencoba menyabarkan diri setelah menangis lima jam penuh malam itu. Syukurlah, seiring tenggelamnya waktu, datangnya peristiwa-peristiwa yang menggembirakan, barangsur-angsur rasa sayangku untuk Kak Willie mencair. Selanjutnya kami tetap menjaga hubungan dalam garis persahabatan yang harmonis. Segala sesuatu kembali bergerak apa adanya.
Mungkin aku termasuk satu dari segelintir perempuan muda yang beruntung. Dari kacamata umum, tidak semua gadis bisa merasakan keluwesan bergaul layaknya yang aku dapat. Ayahku seorang pendeta. Profesi itu tak serta merta menjadikannya sebagai orangtua yang berpikiran kolot. Kami seperti sahabat. Tak ada batas-batas yang kerap membuat seorang anak merasa asing dengan orangtuanya. Aku dengan lugas bisa membagi segala persoalan yang menggumuli hati tanpa khawatir mereka marah atau tersinggung. Bahkan sampai masalah percintaanku mereka tak sungkan membagi saran dan pendapat. Meski dalam hal-hal tertentu aku tetap mengambil jarak. Biasanya hal-hal tertentu itu menyangkut kebahagiaan mereka. Aku tak sanggup membayangkan melihat wajah ayah ibu tak lagi dihiasi senyum kehangatan yang telah kunikmati selama bertahun-tahun. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku juga.
Aku bukan termasuk perempuan yang gemar memendam-mendam perasaan. Itu adalah karakter umum yang mendominasi kepribadian perempuan umumnya. Sebagian besar perempuan lebih memilih tersiksa oleh perasaannya daripada harus berterus terang dan menerima segala resiko yang siap menantang.
Menyerah setelah gagal tak ada dalam kamusku. Untuk kedua kalinya aku jatuh cinta lagi. Hingga saat ini aku tak pernah bisa menjelaskan jika ada yang menanyakan mengapa aku menyukai seseorang. Yang pasti, aku menyukainya karena dia adalah dia. Hanya itu. Persoalan ini mengemuka setelah aku menolak, ketika seorang pria yang bertetangga denganku menyatakan cintanya suatu waktu. Awalnya muncul perasaan risih. Tapi kuputuskan memberanikan diri dan dengan lantang mengatakan kalau hatiku telah tersangkut untuk orang lain. Setelah penampikkan itu, jelas sekali perubahan sikap yang sangat signifikan. Ia tampak membenciku setengah mati. Mengapa sebuah penolakan mesti dianggap sedemikian seriusnya ?. Cinta tak bisa, dan tak akan mungkin bisa dipaksakan. Sebuah paksaan hanya akan menghasilkan kisah romantis yang menjijikkan. Seseorang dengan kedewasaan di atas rata-rata mampu mengerti kenyataan ini.
Suatu saat aku menemukan momen yang pas untuk bersikap jujur dan mengubur dalam-dalam perasaan kikuk. Saat di mana menyatakan cinta bukan lagi pokok yang tabu untuk diutarakan. Dan menurutku ia cukup dewasa menghadapi kondisi seperti itu. Usianya terpaut lumayan jauh denganku. Maklum, ia adalah dosen di kampusku.
Pria itu tetap tenang sesaat setelah kututurkan yang sebenarnya. Ia tidak mengiyakan ataupun menolak. Bahwa ia sudah mempunyai tambatan hati, aku tak ambil peduli. Prinsip kalau cinta harus diperjuangkan menjadi peganganku. Sementara itu ia tetap memberikan harapan. Lewat sikapnya yang mesra dan perhatian yang menunjukkan bahwa, aku juga menyayangimu.
Perlakuan-perlakuan menghanyutkan yang kuterima semakin memperkeruh getaran-getaran rasa di dalam dada. Malam minggu itu pertama kali kami kencan. Aku yang mengajak. Walaupun aku mendapat giliran kedua, karena sebelumnya ia harus main kucing-kucingan dulu dengan pacarnya, membujuk dengan rangkaian kata-kata meyakinkan.
Setiap pasangan yang tengah memadu kasih rasanya mesti lebih kreatif lagi menemukan ritual yang lebih variatif menghabiskan malam panjang. Nonton bioskop, makan malam, merupakan tradisi yang perlu direvolusi. Kegiatan-kegiatan tadi mulai terasa usang dan membosankan. Bagaimana misalnya, jika kita bermalam minggu di puncak gunung?, atau bermesraan di tepi laut sambil memancing ikan?. Dalam alam pikirku semua itu terbayang amat menyenangkan. Namun, lelaki dan perempuan modern cenderung menganggap kegiatan ini lebih menyiksa daripada kerja rodi.
Memang tak ada gagang pancing dalam genggaman kami. Angin laut berhembus dengan gemuruh kesejukkan malam. Bintang-bintang menyulap tempat itu semegah pantai Aleksandria. Satu jam lebih duduk di atas batu besar tak membuat pantatku pegal. Belaian jemarinya yang menyapu rambutku mampu membunuh rasa pegal sedahsyat apapun. Sebagai seorang perempuan, kali itu aku betul-betul merasakan nikmatnya terbenam dalam buaian pesona cinta. Sesuatu yang selama ini masih sebatas bayang-bayang kabur di atas alam khayalku. Keindahan yang hanya sekadar pengisi lamunan setelah selesai menonton film-film drama romantisnya Hollywood. Sebab sejauh ini, menjalin hubungan dengan laki-laki tak lebih dari penggalan-penggalan roman picisan tanpa klimaks cerita. Selesai sebelum bertanding. Berakhir tanpa bumbu-bumbu penyedap.
Ciuman penutupan yang dilayangkannya adalah penghabisan yang membuat seisi bumi seperti mati.
Setiba di rumah kembali sepasang indera penglihatku terjerumus oleh suasana hati. Mereka enggan buru-buru istirahat. Merayakan euforia kebahagiaan hingga akhirnya lelah setelah mentari kembali terjaga. Aku kasmaran. Demikian kalimat singkat yang bisa mendeskripsikan gejolak aneh yang tengah menghantamku saat ini. Namun sesaat segera kuarahkan pikiran untuk tidak tenggelam terlalu jauh. Pengalaman pahit yang mendera sebelumnya bukan pelajaran yang pantas diabaikan. Bukankah ia telah mempunyai pacar ?. Sejauh ini tak ada gejala yang menunjukkan ia akan menegaskan sebuah pilihan. Ia seperti menikmati posisi di antara dua perempuan yang menyayanginya.
Ini kondisi yang tidak baik. Pikirku siang itu di dalam sebuah angkutan kota. Cepat atau lambat hubungan jenis begini harus segera diakhiri. Jenis hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Sialnya, pihak yang diuntungkan itu bukanlah aku. Ya, pria itu yang mereguk kenikmatan dari situasi ini. Barangkali saja ia sedang tersenyum sekarang seraya membangga-banggakan diri di hadapan semua orang telah menundukkan dua wanita sekaligus. Lalu mereka terbahak bersama-sama membayangkan betapa tololnya dua wanita itu.
Mendadak kebahagiaan tadi menjelma menjadi rasa bimbang. Kembali lagi aku diperhadapkan pada sebuah dinding kokoh tanpa jalan keluar. Masalah-masalah yang setelah dikunyah dengan akal sehat, harusnya tak perlu terjadi. Jika sudah berbicara cinta, metode berpikir mengandalkan logika acapkali terpinggirkan. Cinta bahkan mampu membujuk kita terjun ke dalam lubang yang nyata-nyata telah membentang jelas di depan mata kita.
Aku melamun sendiri di teras samping rumah dengan seribu tanya tanpa jawab. Sesekali mempidana diri sendiri dengan jutaan tuduhan yang menggema di lorong hati. Aku memang tak berguna. Dan seperti kata banyak orang, terlalu kekanak-kanakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya dewasa. Sepertinya butuh banyak waktu lagi untukku agar bisa menyikapi segala sesuatu dengan lebih matang. Akhirnya aku mengerti bahwa semuanya memang tak sesederhana yang dibayangkan.
Benakku terus melayang. Mengais-ngais kehampaan dalam ruang yang kaku, membuat pikiranku tanpa sengaja meloncat pada seseorang. Seorang lelaki yang kukenali di sebuah pameran seni instalasi yang digelar seorang seniman lokal tiga minggu silam. Ketika itu aku sedang mengamati setiap karya yang dipamerkan dengan penuh kebingungan. Aku memang salah satu dari sebagaian besar masyarakat kota ini yang memiliki insting buruk dalam menilai karya seni. Kalaupun kunjungan ini bukan agenda wajib mata kuliah seni dan kebudayaan yang kukontrak, mustahil aku berada di sana waktu itu.
Di tengah kebingungan yang tak kunjung mencair seorang lelaki membantuku menjelaskan bagaimana seni instalasi ini. Syukurlah, aku lupa membawa alat tulis, sehingga aksi meminjam pulpen menjadi tonggak terjadinya perbincangan itu. Perbincangan yang selanjutnya terus berlangsung lewat telepon, karena sebelum meninggalkan tempat ini, turut pula kutinggalkan nomor ponselku padanya.
Beberapa kali ia mengajakku menemaninya melihat-lihat novel terbaru di toko buku. Meski pendiam, ia cukup menyenangkan sebagai lelaki. Walau kadang apa yang dibicarakannya sama sekali tak kumengerti. Barangkali karena timpangnya wawasan seni yang kupunya dibanding dirinya.
Tapi saat bersamanya, aku merasakan kenyamanan yang tak biasa. Entahlah, mungkin karena kepribadiannya yang cukup unik jika dibanding lelaki lain. Ia juga tak pernah jenuh menampung keluh kesah yang menguap dari lidahku. Kehangatan itu kerap memaksaku tersenyum-senyum sendiri di dalam kamar. Sebelumnya aku sempat khawatir, jangan-jangan ia sebal dengan perempuan banyak tingkah sepertiku. Namun kekhawatiran tadi ternyata tidak terbukti. Harus kuakui, aku sempat jatuh hati padanya. Ah, apakah ini salah?. Sudah terlalu seringkah aku jatuh hati?. Terlalu mudahkah hatiku dirampas oleh orang lain?. Mungkin memang demikian. Karena itu aku tak terlalu menanggapi serius kata hatiku kali ini. Apalagi saat itu statusku masih sebagai kekasih simpanan si dosen.
Aku pernah mendengar kalimat guyonan yang pernah dilontarkan salah seorang teman. Katanya sesuatu yang diperoleh secara instan, akan terlepas secara instan juga. Apakah ini petanda baik?. Kegagalan-kegagalanku sebelumnya mungkin karena sifatnya yang terlalu instan.
Rasanya cukup. Aku membutuhkan cukup waktu untuk mengintrospeksi diri. Mereshufle cara-caraku dalam menyikapi hidup. Keinginan menggebu-gebu menikmati masa muda dengan bunga-bunga cinta sementara waktu dipendam dulu.
Benarkah komitmen itu bisa terus kupertahankan?. Tampaknya jawaban pertanyaan ini menjadi tak pasti pagi itu.
“Kau tak perlu marah mendengar penuturanku ini” Ucapnya dengan nada datar.
Aku tak mungkin marah. Sampai kapanpun aku tak akan bisa marah pada orang lain. Hatiku terlampau lembut untuk manaruh amarah.
“Barangkali bukan hal penting bagimu. Tapi bagaimanapun harus kukatakan, karena hal ini penting bagiku. Hm.. mungkin tak ada lagi kesempatan lain selain sekarang” Lanjutnya.
Kedua matanya yang tajam seolah selaras dengan pernyataan yang meluncur dari mulutnya. Sungguh di luar daya kiraku ia akan menyatakan cintanya saat itu. Raut yang aku lihat jauh dari kesan main-main. Nada suara itu menandakan ketulusan yang alami. Dan semuanya itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku hilang energi mengeluarkan rangkaian huruf. Harusnya aku bahagia. Karena cinta yang selama ini mengusik alam pikirku telah datang dengan sendirinya. Aku tak perlu repot-repot lagi mencari cinta yang kuimpikan itu. Namun komitmen tetaplah komitmen. Jika aku melanggarnya, maka satu lagi tabiat buruk yang akan menempel, gadis yang plin-plan.
Seperti mendorong sebuah truk seorang diri, dengan berat hati aku mengatakan belum ingin menjalin hubungan, dan ingin menjalani segala sesuatunya sendiri dulu. Meski kukatakan dengan jujur kalau aku menyukainya juga. Setelah masalah demi masalah yang tak henti memagutku, kesadaran yang muncul bahwa aku memang belum siap untuk mencintai dan dicintai.
Ia tersenyum. Senyum sederhana yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tak menyangka ia hanya tersenyum. Tak ada nada sesal atau kecewa yang menguap di wajah itu.
“Terserah kamu saja” responnya singkat lalu kami berpisah.
Ia tampak lega. Setelah menumpahkan isi hatinya ia seperti baru saja menanggalkan sebuah gunung di atas punggungnya. Aku hanya memandanginya dari belakang seakan memandangi ribuan daun kemboja bertebaran di segala penjuru. Kecamuk batin kembali mengaduk-aduk isi otakku. Benarkah keputusan yang kuambil ini?. Yakinkah bahwa ini yang terbaik untukku?
Penyesalan dan keragu-raguan tengah bertarung sengit di dalam batin. Aku terkulai di atas tempat tidur meratapi gelombang tsunami yang tak kunjung surut. Ibu berkali-kali mengetuk pintu menyelidiki apa yang terjadi. Kembali hal itu ia lakukan setelah sepuluh menit berselang. Saat-saat seperti inilah aku merasakan betul betapa bernilainya kehadiran orangtua. Semuanya luluh. Aku membuang jauh kegagahan yang selalu kupasang di hadapan ayah dan ibu. Karenina yang tak pernah menangis di depan mereka terbang jauh ke ujung bumi. Dalam lingkaran lengannya ibu menumpahkan sejuta kehangatan, menyuntikku dengan tetesan-tetesan semangat menatap hari depan.
“Cinta seperti musim. Dan manusia harus pandai mengawinkan rasa yang tepat di musim yang tepat” ucap ibuku dengan kepuitisan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Aku tak pernah tahu ibuku mengoleksi kata-kata seperti itu.
“Setiap orang punya kesempatan mendapatkan kebahagiannya. Jangan pernah menyesal sepanjang hidup hanya karena mengabaikan satu dari sedikit kesempatan itu. Tapi ingat, di setiap musim cinta selalu punya warnanya sendiri” lanjut ibu hangat.
Setelah itu aku bisa tidur nyenyak. Seolah merasakan kembali nikmatnya tidur yang akhir-akhir ini lenyap. Dengan sejumput asa untuk menyambut hari esok dengan secuil senyum.
Memang benar. Pagi begitu menyenangkan. Cicitan nuri terdengar semerdu simfoni Mozart. Angin pagi yang menggelayut menerpa sejuk di setiap sisi kamarku yang berantakan. Dedaunan menggigil tertimpa cakrawala yang tengah siap-siap menumpahkan dendamnya. Aku tak gentar sedikitpun. Keinginanku untuk mencicipi udara luar hari ini berbanding lurus dengan ketidaksabaranku untuk cepat-cepat menemuinya. Lebih baik kalau aku ke rumahnya saja. Hari sabtu pagi biasanya ia hanya menghabiskan waktu dengan membaca atau nonton serial anak di rumah. Pernah kupergoki aktifitas ini tatkala mengembalikan buku filsafatnya yang kupinjam dua minggu lalu.
Seorang wanita separuh uzur membuka pintu. Aku memaku sejenak. Setahuku ia hanya tinggal berdua bersama kakak perempuannya. Ibunya telah lama meninggal hingga tak mungkin ada wanita lain di rumah ini.
“Mereka berdua sudah kembali ke tempat tinggal ayahnya kemarin. Pesawatnya berangkat tengah malam” ucap wanita yang rupanya penghuni baru rumah itu.
“Tidak ada apa-apa. Cuma ingin berkunjung” balasku singkat seraya melangkahi pagar besi tua yang mengurung halaman rumah. Hujan yang perlahan kian menderas tak menghasut kedua kakiku untuk mempercepat langkah. Linangan air mata tak lagi terasa getirnya karena bercampur aduk dengan gemuruh air hujan. Setelah sekian lama malam itu akhirnya aku menulis catatan harian lagi. Kata-kata mengalir baris demi baris memenuhi deretan halaman yang lama tak terisi. Tak seorangpun bisa mengetahui isi catatan ini. Hanya aku yang berhak. Catatan dengan judul yang kutulis besar-besar, “LOVE IS SUCKS”.
Dua gereja baru menunjukkan jalan menuju toleransi beragama
-
Pemerintah harus mengubah atau mencabut peraturan yang mendiskriminasi
minoritas agamaAndreas HarsonoBanten NewsGereja Bersama, multi denominasi,
dan Gerej...
2 bulan yang lalu




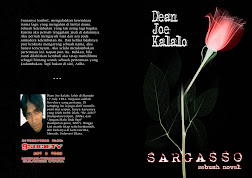



.jpg)




0 komentar:
Posting Komentar