 Dunia pendidikan kita saat ini seolah menghadapi situasi-situasi yang mengenaskan, dan kalau mau jujur dan lapang dada mengakui, memang absurd. Namun sejak dahulu kala kita berusaha mengingkari keabsurdannya, dan terus tertidur di atas ranjang hegemoni pendidikan yang tak masuk akal itu. Bukan apa-apa, di sanalah nafas kita bertumpu, di sanalah pengakuan sebagai manusia ditegakkan, dan di sanalah seolah-olah jati diri kita sebagai mahluk mulia bertengger. Sementara teror yang terus membuntuti kita bahwa di dalam “dunia pendidikan” itu akal budi kita ditindas. Eksisitensi manusia yang memiliki kehendak bebas berpikir dipasung, dalam sebuah format paten yang tersistem dalam bentuk lembaga pendidikan. Dan kenyataan yang lebih mengerikan lagi bahwa kita tak henti-hentinya mengorbankan energi dan materi untuk upah ketertindasan itu.
Dunia pendidikan kita saat ini seolah menghadapi situasi-situasi yang mengenaskan, dan kalau mau jujur dan lapang dada mengakui, memang absurd. Namun sejak dahulu kala kita berusaha mengingkari keabsurdannya, dan terus tertidur di atas ranjang hegemoni pendidikan yang tak masuk akal itu. Bukan apa-apa, di sanalah nafas kita bertumpu, di sanalah pengakuan sebagai manusia ditegakkan, dan di sanalah seolah-olah jati diri kita sebagai mahluk mulia bertengger. Sementara teror yang terus membuntuti kita bahwa di dalam “dunia pendidikan” itu akal budi kita ditindas. Eksisitensi manusia yang memiliki kehendak bebas berpikir dipasung, dalam sebuah format paten yang tersistem dalam bentuk lembaga pendidikan. Dan kenyataan yang lebih mengerikan lagi bahwa kita tak henti-hentinya mengorbankan energi dan materi untuk upah ketertindasan itu.
Seonggok ungkapan kekesalan di atas mungkin akan terkesan mengada-ada dan mengundang amarah bagi banyak orang. Entah orangtua, yang menjadi salah satu korban dari kenyataan ini, para guru maupun dosen, atau sang objek utama yaitu peserta didik itu sendiri. Kemungkinan lain yang akan timbul adalah rasa malu atau justru sikap masa bodoh dari sebagian masyarakat kita yang rata-rata fatalis. Kemudian, timbul pelarian klasik dari sebuah permasalahan, mencari kambing hitam. Siapakah sebenarnya yang harus bertanggungjawab? Apakah pemerintah, sistem pendidikan, orangtua, pengajar, atau yang diajarkah?. Memang semuanya rumit dan kompleks.
Sejauh pengamatan saya ada beberapa tipe perilaku dari siswa atau peserta didik, pertama ialah siswa atau mahasiswa yang menganggap kegiatan belajar di sekolah atau kampus sebagai beban yang harus diselesaikan setiap hari. Sehingga aktivitas-aktivitas seperti mengerjakan tugas, memahami pelajaran, tak beda dengan kerja rodi. Namun tipe ini terbentur pada kenyataan bahwa ia harus memenuhi tuntutan orangtua, bahwa kelangsungan hidupnya tergantung dari orangtua. Maka ia menjalani bertahun-tahun masa sekolahnya dengan rasa stres. Dan prestasi yang cukup membanggakan, toh ia bisa juga menyelesaikannya. Yang kedua ialah tipe pelajar yang menyadari bahwa aktivitas belajar adalah sesuatu yang menyenangkan, meskipun ia harus mengerjakan setumpuk soal-soal pelajaran dengan rasa lelah hingga larut malam, ia tetap setia melakukannya karena ia menikmatinya. Mereka yang masuk dalam kategori ini biasanya sang jawara-jawara kelas.
Yang kedua ialah tipe pelajar yang menyadari bahwa aktivitas belajar adalah sesuatu yang menyenangkan, meskipun ia harus mengerjakan setumpuk soal-soal pelajaran dengan rasa lelah hingga larut malam, ia tetap setia melakukannya karena ia menikmatinya. Mereka yang masuk dalam kategori ini biasanya sang jawara-jawara kelas.
Yang ketiga adalah tipe siswa yang cukup mempunyai keinginan untuk belajar, namun seringkali menemui kesulitan karena diperhadapkan pada tidak efektifnya metode pengajaran sang pengajar, atau mungkin kemampuannya untuk menangkap suatu intisari pelajaran yang lemah. Tipe seperti ini bukan berarti bodoh. Namun ia perlu bimbingan ekstra dari guru maupun orangtua. Tipe seperti ini biasanya sangat rentan diserang penyakit “gampang menyerah” apabila kendala-kendala tadi tidak teratasi.
Yang keempat adalah tipe siswa masa bodoh. Apakah ia mempunyai kemampuan menangkap pelajaran atau tidak. Ia tetap menganggap aktifitas ini hanyalah membuang-buang waktu.
Dari keempat tipe di atas semuanya mempunyai kelemahannya masing-masing, dengan takarannya masing-masing. Bahkan, tipe yang kedua pun mempunyai kelemahannya, yaitu orientasi belajar yang belum tercerahkan. Ia belum tahu arah yang akan dituju dengan bekal ilmu dan kepandaian yang ia miliki. Apakah untuk mendapatkan pekerjaan?, uang? Yang pasti untuk menggapai cita-cita. Nah, apa sebenarnya hakekat cita-cita itu?
Para guru, dosen, atau orangtua mungkin seringkali mendapati anak didiknya berperilaku seperti keempat tipe tadi. Selain pengaruh karakter bawaan, sebagian besar perilaku itu lebih dipengaruhi situasi psikologis yang datang dari keluarga maupun lingkungan di mana ia menjalani kehidupan sosial. Persoalan belajar adalah persoalan mental atau kepribadian. Plato menyebutnya dengan “mengejar sang baik” dengan menggunakan akal budi. Memburu ilmu pengetahuan merupakan salah satu upaya manusia untuk mengejar sang baik itu. Karena manusia adalah baik adanya. Jadi ketika kita tidak berperilaku baik berarti kita tidak sedang menjalani fitrah kita sebagai manusia. Sederhanya, siapapun yang tidak belajar berarti ia tidak manusiawi.
Daripada sibuk memperdebatkan masalah sistem pendidikan kita yang absurd itu. Sebaiknya kita membuka pemahaman bahwa hakekat sesungguhnya aktifitas belajar itu ada dalam diri sendiri. Sebagaimana lembaga-lembaga pada umumnya, maka lembaga pendidikanpun tak pernah terlepas dari ketidakberesan. Perlu usaha keras dari semua pihak untuk mengubahnya. Yang terpenting bukan masalah sistem pendidikan, tapi bagaimana kita dapat membentuk diri sebagai pribadi yang “pembelajar”. Seorang pembelajar tidak akan menggantungkan kebutuhan ilmu pengetahuannya hanya dari sekolah saja, tapi ia memetik kebijaksanaan dan kecerdasannya dari segala ranah kehidupan. Termasuk sekolah tentunya. Karena manusia yang cerdas tidak saja hanya sukses menaklukan rentetan kurikulum akademik, (bahkan yang menaklukannya pun belum tentu cerdas) yang puncaknya adalah pembubuhan gelar di depan atau belakang nama, tapi juga mampu menaklukan tantangan-tantangan sosial, kebudayaan, dan bahkan keluarga yang dijalaninya sebagai seorang manusia.
Membentuk diri menjadi pribadi yang “pembelajar” itu memang tidak semudah menggerakan jari-jemari. Perlu usaha keras yang sebaiknya dilakukan sejak dini. Pihak yang paling berpengaruh adalah orangtua. Dan orangtua adalah guru yang paling menentukan dan yang paling berpengaruh bagi perkembangan seorang anak. Perkataan orangtua adalah kebenaran yang tak terbantahkan bagi anak-anaknya. Untuk itu orangtua dituntut untuk membangun mental, serta mengawasi dan membimbing arah berpikir dan orientasi berperilaku dari seorang anak. Kebiasaan dan disiplin yang sudah ditanamkan sejak dini akan terbawa hingga perkembangannya menjadi pribadi yang dewasa. Banyak yang menyebutkan kalau anak adalah hasil buah karya orangtuanya. Memang tidak salah. Selain mewarisi darah, seorang anak juga mewarisi unsur-unsur nilai yang didapatkan melalui interaksi dengan orangtuanya.
Hal penting yang perlu diperhatikan orangtua dalam mendidik anak di antaranya, mengantisipasi pengaruh media, khususnya media elektronik audio visual. Anak-anak sampai remaja kesehariannya tak pernah lepas dari menonton televisi. Sementara media yang satu ini mempunyai andil yang sangat besar dalam membentuk stereotip-stereotip di kalangan mereka.
Kita tahu bersama bahwa sebagian besar isi materi siaran stasiun-stasiun televisi di Indonesia lebih berorientasi meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan menghadirkan tontonan yang memanjakan khalayak. Stasiun-stasiun televisi kita memanfaatkan kondisi masyarakat yang sebagian besar berkutat dengan kemiskinan, di mana kehidupan kesehariannya hanya berpikir bagaimana mendapatkan sesuap nasi hari ini. Dalam situasi krisis seperti tadi masyarakat membutuhkan tontonan yang ringan dan memanjakan pikiran. Lalu munculah tayangan-tayangan yang samasekali tidak menghiraukan kualitas, yang menyeret masyarakat kita untuk terus hidup di dalam mimpi (bukannya bermimpi).
Selain media, pengaruh besar yang lain adalah lingkungan. Di sini saya bukan bermaksud mengajak setiap orangtua agar mendidik anaknya untuk “pilih-pilih bergaul”. Tapi sebelum ia dilepas pada pergaulan sosial yang konon lebih garang dari hutan rimba. Pihak orangtua wajib memberikan pembekalan mental maupun disiplin diri agar si buah hati dapat mengendalikan, bukannya dikendalikan oleh kebudayaan kita yang kadang memang mencurigakan. Paulo Freire mengatakan bahwa kebudayaan kita sangat sarat dengan muatan-muatan ideologi yang secara massal membentuk tatanan sosial di masyarakat. Ini bukan berarti kita sebagai individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus terseret pada skenario besar tadi. Ia menambahkan kita bisa membentuk kebudayaan sendiri tanpa terpengaruh pada kebudayaan yang ia sebut “kebudayaan bisu” itu.
Usaha yang keras dari setiap orangtua niscaya akan melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh untuk anak-anak di masa depan, serta melahirkan individu-individu yang cerdas serta memiliki kepekaan yang tinggi pada realitas sosial yang dihadapinya. Dan niscayanya lagi setiap orangtua tak perlu repot-repot memaksa buah hatinya untuk tekun belajar, karena dengan sendirinya mereka akan mengejar ilmu setinggi mungkin, karena kesadaran akan fitrahnya sebagai manusia yang mempunyai akal budi sudah terlanjur tertanam.***
Dua gereja baru menunjukkan jalan menuju toleransi beragama
-
Pemerintah harus mengubah atau mencabut peraturan yang mendiskriminasi
minoritas agamaAndreas HarsonoBanten NewsGereja Bersama, multi denominasi,
dan Gerej...
4 minggu yang lalu




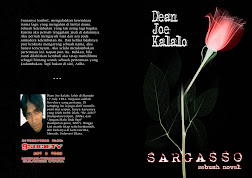



.jpg)





0 komentar:
Posting Komentar