 Ditinjau lewat aspek penokohan, maka akan ditemukan bahwa Diva adalah tokoh utama dalam novel ini. Sosok bintang jatuh yang digambarkan pengarang (Dewi Lestari) maupun pencerita (Dhimas dan Ruben) tak lain adalah perempuan cantik yang sering menjajahkan tubuhnya kepada banyak lelaki ini. Menurut kacamata masyarakat umum, apalagi dalam konteks budaya Indonesia, perempuan yang menjajahkan tubuhnya pada lebih dari satu lelaki tanpa ada ikatan resmi dan menerima imbalan berupa uang disebut pelacur.
Ditinjau lewat aspek penokohan, maka akan ditemukan bahwa Diva adalah tokoh utama dalam novel ini. Sosok bintang jatuh yang digambarkan pengarang (Dewi Lestari) maupun pencerita (Dhimas dan Ruben) tak lain adalah perempuan cantik yang sering menjajahkan tubuhnya kepada banyak lelaki ini. Menurut kacamata masyarakat umum, apalagi dalam konteks budaya Indonesia, perempuan yang menjajahkan tubuhnya pada lebih dari satu lelaki tanpa ada ikatan resmi dan menerima imbalan berupa uang disebut pelacur.
Encyclopaedia Britannica (dalam Dam Truong, 1992:15) mendefinisikan pelacuran sebagai:
“praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran dikarakterisasikan oleh tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidak acuhan emosional”
Definisi tersebut khususnya tiga unsur yang dipaparkan di atas sangat sesuai dengan karatkteristik yang terdapat pada tokoh Diva. Meskipun definisi ini mempunyai kelemahan karena dua dari tiga unsur tadi tidak bisa diterapkan di semua situasi. Kita tidak bisa mengatakan setiap aksi pelacuran selalu dilandasi ketidak acuhan emosional ataupun pembayaran. Bagaimana dengan kasus ketika seorang perempuan melakukan hubungan intim dengan banyak lelaki (tanpa ikatan resmi), namun ia sendiri melibatkan unsur emosional dan menerima bayaran?. Jelas bahwa dalam hal ini kriteria ekonomi semata juga memang tidaklah memadai. Kita juga tidak bisa mengatakan bila hubungan intim dalam sebuah ikatan resmi sama sekali bebas dari tindakan pembayaran. Banyaknya tarik menarik mengenai konsepsi pelacuran oleh banyak ilmuwan dikarenakan setiap konsep tidak selalu bisa diterapkan pada semua kebudayaan masyarakat. Semua bergantung dari etos budaya yang terdapat di pusat konstruksi sosial norma-norma seksual (Dam Truong, 1992:13).
Secara lebih luas istilah pelacur kadang ditempelkan kepada seseorang yang menjual keahliannya untuk sesuatu yang tak berharga. Contohnya, seorang seniman yang mempunyai potensi besar di bidangnya, namun lebih condong membuat karya-karya yang sifatnya komersil. Ia dianggap melacurkan diri karena mengorbankan idealismenya. Di dalam etika kristen juga terdapat makna pelacuran yang lebih luas, yakni tindakan penyembahan terhadap dewa-dewa lain selain Allah. Hal ini dijelaskan dalam kitabYehezkiel pasal 23 dan kitab Hosea (1:2-11).
Dijelaskan Ihsan (dalam Wakhudin) para antropolog mengatakan, adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah terjadi sejak zaman primitif, menyebabkan pelacuran menjadi realitas yang tak mungkin terelakkan. (http://akhmadsudrajat.wordpress.com) Tugas perempuan diarahkan untuk melayani kebutuhan seks lelaki. Sedangkan kaum feminis menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pelacuran karena kuatnya sistem dan budaya patriarkhi. Sementara kaum marxis menganggap pelacuran merupakan resiko dari sistem kapitalisme.
Pada perkembangannya kedudukan pelacur mengalami naik turun. Menurut sejarah, bentuk pelacuran tertua ditemukan di negara-negara kuno seperti India dan Babilonia Kuno (Dam truong, 1992:20). Waktu itu tindakan pelacuran identik dengan berbagai ritus keagamaan. Sebagai contoh di Babilonia Kuno, perempuan-perempuan yang berafiliasi dengan monumen yang dianggap keramat, seperti candi, melakukan hubungan seks (melacurkan diri) dengan para pengunjung tempat tersebut. Hal ini sebagai wujud pemujaan atas kesuburan dan kekuasaan seksual para dewi. Untuk hal tersebut diberikan sumbangan untuk candi. Contoh lain ditambahkan Ihsan (dalam Wakhudin), adalah perempuan-perempuan yang menjajahkan dirinya diberbagai tempat, dan penghasilannya diberikan kepada pendeta untuk kepentingan kuil. (http://akhmadsudrajat.wordpress.com). Mereka dikenal dengan istilah “pelacur kuil” (temple prostitutes).
Pelacuran zaman tersebut identik dengan pengabdian untuk kepentingan keagamaan. Jadi, kedudukan sosialnya dianggap terhormat. Contoh lain yang tidak ada hubungannya dengan religi terdapat di negara-negara Asia Timur. Di Jepang terkenal dengan Geisha, perempuan penjajah seks yang dibekali dengan berbagai kemampuan seni, seperti memainkan bermacam alat musik, menari, berpuisi, dan lain-lain. Geisha berasal dari kata Gei yang artinya seni, dan Sha yang berarti pribadi. Budaya Jepang menganggap Geisha adalah artis. Perempuan-perempuan yang menjadi Geisha memiliki latarbelakang kelas yang beragam. Namun, pengaruh sosial dan hak istimewa yang mereka dapatkan tergantung juga dengan pria siapa mereka melakukan hubungan. Dari contoh tadi kita bisa melihat, demi kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan keagamaan dan penguasa, pelacuran tidak dicerca melainkan menjadi sesuatu yang dihargai.
Pelacuran di mata masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang buruk, haram, hina, dan lain-lain. Wanita yang menjadi pekerja seks dianggap sebagai sampah masyarakat, perusak moral, penyebar berbagai macam penyakit. Baik agama maupun hukum melarang praktek prostitusi. Meski, di daerah-daerah tertentu seperti Surabaya terdapat lokalisasi PSK yang legal. Augustinus dari Hippo 354-430), seorang bapak gereja pernah mengatakan bahwa, pelacuran itu ibarat "selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya."(http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran). Sesuatu yang ironi memang, ternyata di tengah stigma yang disandangnya, pelacur juga dibutuhkan, dan sebagai solusi dari sebuah problem sosial untuk mengurangi kasus-kasus pemerkosaan di tengah masyarakat. Anggota masyarakat yang menggunakan jasa pekerja seks sama sekali tak menanggung stigma seperti yang dikenakan pada pelacur.
Rowbothan (dalam Dam Truong, 1992:17) berpendapat bahwa istilah pelacuran merupakan perwujudan dari hegemoni kultural. Pemisahan antara istri (perempuan terhormat, gundik (perempuan piaraan), pelacur (perempuan sundal) tak lain demi kepentingan dominasi pria. Karakter Diva, berkaitan dengan pendapat tadi bisa dikatakan sebagai media pengarang untuk melawan hegemoni kultural tersebut. Diva berprofesi sebagai peragawati kelas atas. Imbalan yang dimintanya setiap kali naik panggung jumlahnya tidak sembarangan. Di samping itu, ia juga selektif dalam memilih acara. Bahkan, hanya majalah-majalah bona fide saja yang bisa memamerkan foto-fotonya. Standar tinggi tersebut sepadan dengan profesionalitas dan disiplin yang dijalankannya. Hingga kesan yang akan timbul selanjutnya adalah Diva tipe perempuan pekerja keras dan konsisten dengan pekerjaannya. Tokoh Diva merupakan refleksi pengarang akan kenyataan yang sudah menjadi rahasia umum dalam kehidupan kota metropolitan, banyaknya model yang juga berprofesi sebagai wanita penghibur. Pelacuran terselubung kelas tinggi yang hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, yaitu mereka yang memiliki kemampuan ekonomi mapan. Satu hal yang menarik, sebagian dari para pelacur ini memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Jadi, menganggap masalah ekonomi sebagai satu-satunya faktor yang melatarbelakangi tindakan pelacuran adalah keliru. Banyak faktor lain yang bisa dkatakan menjadi penyebab, seperti lingkungan pergaulan, gaya hidup yang konsumtif (membuat setiap orang ingin memperoleh uang dengan cepat dan mudah), lingkungan keluarga, dan lain-lain.
Diva memiliki hubungan intim dengan beberapa lelaki, dan ia juga menuntut upah untuk hubungan tersebut. Dari seorang pengusaha kaya bernama Dahlan hingga seorang pemuda kaya beristeri seperti Nanda. Tindakan “menjual diri” tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak terhormat. Ia mempunyai sebuah pembenaran yang ia yakini sebagai dasar pemikiran atas tindakannya itu. Kemampuan berpikir dan luasnya wawasan yang dimiliki Diva memang sangat kontradiktif dengan profesi sampingan yang dijalankannya. Bagaimana mungkin perempuan cerdas dan berkepribadian kuat seperti dirinya rela menjual tubuhnya untuk dinikmati banyak lelaki?. Tapi ia pun memiliki pembenaran atas semua itu. Gambaran ideologi yang mendasari pilihan hidupnya terdapat dalam kutipan berikut ini:
“Wanita itu tersenyum mencemooh. “Justru karena saya lebih pintar dari kamu dan CEO kamu, makanya saya tidak mau bekerja seperti kalian. Apa bedanya profesi kita? Sudah saya bilang, kita sama-sama berdagang. Komoditasnya saja beda. Apa yang kamu perdagangkan buat saya tidak seharusnya dijual. Pikiran saya harus dibuat merdeka. Toh, berdagang pun saya tidak sembarang...”(2001: 57).
Dari perkataan tokoh tersebut bisa dilihat konsep ideologi yang dipegang olehnya. Bagi Diva, apa yang diperdagangkan oleh para kapitalis adalah sesuatu yang seharusnya tidak dijual, karena sesuai dengan prinsip marxisme, semua itu seharusnya adalah kepemilikan bersama. Sementara ia sendiri menjual tubuhnya, kecantikannya, menurutnya adalah sesuatu yang wajar. Karena keindahan tubuh dan kecantikannya adalah miliknya sendiri. Ia memiliki kemerdekaan untuk menjualnya kepada siapapun.
Diva adalah tipe perempuan yang nyaris sempurna. Memiliki kecantikan, keindahan tubuh, karir yang sukes, kecukupan ekonomi, kecerdasan, dan menjunjung tinggi kebebasan perempuan. Selain itu, ia juga perfeksionis dalam segala hal, baik dalam hal pekerjaan, maupun pandangan tentang hidup. Namun, ia pun sadar, ia hidup pada masa ketika uang memiliki peranan utama bagi setiap orang untuk dapat mempertahankan diri. Semua hal yang ia lakukan baginya adalah resiko hidup di zaman kapitalis, termasuk “memperdagangkan” tubuhnya sendiri:
“Ia tahu, pekerjaannya membutuhkan fisik yang selalu fit, penampilan yang prima. Tapi semua itu dilakukannya semata-mata karena ia merasa berkewajiban mengurus jasad – kendaraannya untuk menghadapi hidup. Dan kendaraan ini bukan kendaraan rombeng. Ia tidak akan pernah memperlakukannya demikian. Setiap tubuh adalah perangkat yang luar biasa menakjubkan.” (2001:92).
Di zaman kapitalis manusia hampir tidak lagi mempedulikan masalah ketulusan cinta dan hati nurani. Segala sesuatu diukur dengan uang. Orang kaya semakin kaya, dan orang miskin makin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan. Bila ingin tetap bertahan hidup semua orang harus rela membiarkan dirinya terseret dalam arus tersebut. Tapi, Diva beranggapan bahwa bagaimana pun cinta tak akan bisa diperjualbelikan. Nanda, lelaki beristri yang berkencan dengannya, sangat mengagumi kepribadian Diva. Hingga ia pun mengatakan, ia lebih memilih uangnya dibayar untuk merasakan kasih sayang Diva, daripada bersetubuh dengannya:
“Ketulusan bukan ketulusan lagi kalau kita mulai memperjualbelikannya. Saya memang punya dagangan, sama seperti kamu. Kita sama-sama harus begitu untuk bertahan di dunianya tukang dagang. Tapi jangan cemari satu-satunya jalan pulangmu untuk keluar dari semua sampah ini, kembali ke diri kamu sebenarnya. Sorot mata yang hidup tadi, digerakkan kejujuran yang berontak dari dalam sana. Terkutuklah Diva si pelacur begitu ia mulai memunguti uang di atasnya. Ya, terkutuklah dia.” (2001:66).
Karakteristik tokoh yang paradoksal merupakan ciri khusus novel ini. Eksplorasi jenis tokoh seperti ini tampaknya dilakukan dengan sadar oleh pengarang, sebagai perlawanan terhadap norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam kacamata masyarakat, tindakan pelacuran pada umumnya dilatar belakangi pergaulan yang tidak baik atau kondisi ekonomi yang di bawah standar. Anggapan ini jelas sangat bertolak belakang dengan karakteristik seorang Diva. Sebagai seorang peragawati papan atas, kondisi ekonomi yang menopangnya cukup memadai. Di dalam cerita juga tidak digambarkan jika dirinya memiliki pergaulan buruk, yang menyeretnya pada kebiasaan seperti itu. Diva bahkan ditampilkan pengarang sebagai sosok perempuan cerdas dan memiliki wawasan luas, juga peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Stigma yang menempel pada pelacur coba dijungkirbalikan pengarang lewat tokoh Diva, namun di sisi lain, sang pengarang pun tidak bermaksud untuk mengubahnya menjadi positif, yang ditonjolkan di sini adalah sebuah sikap, pemikiran yang dimiliki sang tokoh.
Dua gereja baru menunjukkan jalan menuju toleransi beragama
-
Pemerintah harus mengubah atau mencabut peraturan yang mendiskriminasi
minoritas agamaAndreas HarsonoBanten NewsGereja Bersama, multi denominasi,
dan Gerej...
4 minggu yang lalu




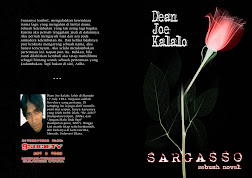



.jpg)





0 komentar:
Posting Komentar