
Tokoh-tokoh tersebut adalah Wayan Togog, Bilung, dan Koba. Mengingat keberadaan mereka di dalam negeri sangat terancam, Yasmin dan teman-temannya memutuskan untuk melarikan mereka ke luar negeri. Demi tujuan tersebut mereka membutuhkan satu orang lain yang sudah berada di luar negeri untuk membantu pelarian ini. Orang yang membantu mereka adalah Saman.
Di bagian ini Ayu Utami mengungkap kronologi dan beberapa hal yang menyangkut peristiwa tersebut. Poin utama yang diungkapkannya adalah bagaimana keterlibatan pemerintahan orde baru dalam sengketa internal yang terjadi antara Partai Demokrasi Indonesia kubu Megawati Soekarnoputri, dan kubu Soerjadi:
“Meskipun para penyerbu kantor DPP PDI menggunakan atribut partai, nyata indikasi keterlibatan aparat militer orde baru di sini. Nama Megawati Soekarnoputri mulai muncul sebagai simbol perlawanan terhadap Suharto sejak ia secara de facto menjadi ketua umum partai dalam musyawarah nasional luar biasa di Surabaya, yang disahkan Kongres III di Kemang, Jakarta, tahun 1993. Sejak itu wanita pendiam ini berpotensi menjadi ancaman bagi Suharto dalam Pemilu 1997 mendatang. Pemerintah Suharto mencoba menjatuhkan putri presiden pertama itu dengan merekayasa perlawanan dari dalam yang berpuncak pada kongres IV di Medan Pertengahan Juni 1996 lalu. Kongres ini mengangkat kader jenggot Soerjadi menjadi ketua umum partai.” (Larung, 2002:176).
Kutipan di atas bisa dilihat bahwa peristiwa 27 Juli 1996 adalah sebuah strategi politik yang dilakukan rezim orde baru demi kepentingan kelanggengan kekuasaannya. Indikasi-indikasi keterliban Suharto dalam perebutan secara paksa kantor DPP PDI Jakarta Pusat yang dikuasai kubu Megawati terdapat dalam kutipan berikut:
“Beberapa saksi mata mengatakan, Komandan Kodim Jakarta Pusat Letkol. Zul Effendi terlihat berada di sana dan ikut mengatur menit-menit awal penyerbuan.
Sepuluh menit kemudian sekitar 500 personil pasukan anti huru hara berseragam lengkap telah tiba. Kapolres Jakarta Pusat Letkol. Abu Bakar bersama mereka. Pasukan membagi diri menjadi dua kelompok, dan menutup lokasi kejadian di ruas Megaria dan jalan Surabaya. Akibatnya, pendukung Mega dari luar lokasi tak bisa memberi bantuan. Di lokasi, penyerangan terhadap markas PDI terus berlangsung. Setelah lebih kurang sepuluh menit dua panser AD ditempatkan
di bawah jembatan layang kereta api.” (Larung, 2002:174). Lewat kutipan di atas dapat dilihat bahwa penyerbuan tersebut dilakukan secara terencana, dan disiapkan secara matang. Keterlibatan TNI maupun POLRI adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, terutama di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, dan Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung dibakar massa yang tak terkendali. Selain terjadi sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia, hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan data bahwa dalam tragedi ini, 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan.
Lewat kutipan di atas dapat dilihat bahwa penyerbuan tersebut dilakukan secara terencana, dan disiapkan secara matang. Keterlibatan TNI maupun POLRI adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, terutama di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, dan Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung dibakar massa yang tak terkendali. Selain terjadi sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia, hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan data bahwa dalam tragedi ini, 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan.
Keterlibatan pemerintah orde baru juga diungkapkan Komnas HAM seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini:
“Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.
Dokumen tersebut juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI bersama Alex Widya S. Diduga, Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo untuk melakukan penyerbuan. Seperti tercatat di dokumen itu, rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-Kongres Medan. Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000.” (http://id.wikipedia.org/wiki/peristiwa 27- Juli.htm)”.
Pemerintah orde baru pada peristiwa tersebut mencoba memanipulasi fakta sejarah dengan menjadikan para aktivis PRD sebagai kambing hitam yang menjadi dalang dari kerusuhan ini. Akibatnya beberapa aktivis PRD dijebloskan ke dalam penjara. Pemerintah dengan ini mencoba membentuk opini publik untuk menutupi keterlibatan mereka:
“Wayan Togog, Bilung, dan Koba ada di Jakarta bulan Juli lalu. Dan seperti Budiman Sudjatmiko serta yang lain, mereka juga terpanggil untuk berbicara di mimbar bebas jalan Diponegoro, di depan kantor PDI, saling memperkuat antara orang-orang yang melawan Suharto. Di situlah intel-intel mencatat dan merekam wajah mereka.” (Larung, 2002:183).
Setelah rezim orde baru tumbang proses hukum untuk menyelesaikan masalah ini juga terkesan angin-anginan. Beberapa tokoh militer yang dianggap terlibat pun divonis bebas oleh pengadilan. Tidak tuntasnya penyelesaian kasus ini adalah cermin penegakan hukum di Indonesia yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari sini masyarakat bisa melihat, bila sudah berhadapan dengan penguasa, hukum pun tidak bisa berbuat apa-apa. Peristiwa 27 Juli juga mencerminkan karakteristik kediktaktoran pemerintahan orde baru yang selalu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.
Dua gereja baru menunjukkan jalan menuju toleransi beragama
-
Pemerintah harus mengubah atau mencabut peraturan yang mendiskriminasi
minoritas agamaAndreas HarsonoBanten NewsGereja Bersama, multi denominasi,
dan Gerej...
4 minggu yang lalu




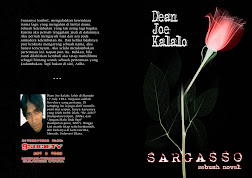



.jpg)





0 komentar:
Posting Komentar