
Tokoh-tokoh tersebut adalah Wayan Togog, Bilung, dan Koba. Mengingat keberadaan mereka di dalam negeri sangat terancam, Yasmin dan teman-temannya memutuskan untuk melarikan mereka ke luar negeri. Demi tujuan tersebut mereka membutuhkan satu orang lain yang sudah berada di luar negeri untuk membantu pelarian ini. Orang yang membantu mereka adalah Saman.
Di bagian ini Ayu Utami mengungkap kronologi dan beberapa hal yang menyangkut peristiwa tersebut. Poin utama yang diungkapkannya adalah bagaimana keterlibatan pemerintahan orde baru dalam sengketa internal yang terjadi antara Partai Demokrasi Indonesia kubu Megawati Soekarnoputri, dan kubu Soerjadi:
“Meskipun para penyerbu kantor DPP PDI menggunakan atribut partai, nyata indikasi keterlibatan aparat militer orde baru di sini. Nama Megawati Soekarnoputri mulai muncul sebagai simbol perlawanan terhadap Suharto sejak ia secara de facto menjadi ketua umum partai dalam musyawarah nasional luar biasa di Surabaya, yang disahkan Kongres III di Kemang, Jakarta, tahun 1993. Sejak itu wanita pendiam ini berpotensi menjadi ancaman bagi Suharto dalam Pemilu 1997 mendatang. Pemerintah Suharto mencoba menjatuhkan putri presiden pertama itu dengan merekayasa perlawanan dari dalam yang berpuncak pada kongres IV di Medan Pertengahan Juni 1996 lalu. Kongres ini mengangkat kader jenggot Soerjadi menjadi ketua umum partai.” (Larung, 2002:176).
Kutipan di atas bisa dilihat bahwa peristiwa 27 Juli 1996 adalah sebuah strategi politik yang dilakukan rezim orde baru demi kepentingan kelanggengan kekuasaannya. Indikasi-indikasi keterliban Suharto dalam perebutan secara paksa kantor DPP PDI Jakarta Pusat yang dikuasai kubu Megawati terdapat dalam kutipan berikut:
“Beberapa saksi mata mengatakan, Komandan Kodim Jakarta Pusat Letkol. Zul Effendi terlihat berada di sana dan ikut mengatur menit-menit awal penyerbuan.
Sepuluh menit kemudian sekitar 500 personil pasukan anti huru hara berseragam lengkap telah tiba. Kapolres Jakarta Pusat Letkol. Abu Bakar bersama mereka. Pasukan membagi diri menjadi dua kelompok, dan menutup lokasi kejadian di ruas Megaria dan jalan Surabaya. Akibatnya, pendukung Mega dari luar lokasi tak bisa memberi bantuan. Di lokasi, penyerangan terhadap markas PDI terus berlangsung. Setelah lebih kurang sepuluh menit dua panser AD ditempatkan
di bawah jembatan layang kereta api.” (Larung, 2002:174). Lewat kutipan di atas dapat dilihat bahwa penyerbuan tersebut dilakukan secara terencana, dan disiapkan secara matang. Keterlibatan TNI maupun POLRI adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, terutama di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, dan Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung dibakar massa yang tak terkendali. Selain terjadi sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia, hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan data bahwa dalam tragedi ini, 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan.
Lewat kutipan di atas dapat dilihat bahwa penyerbuan tersebut dilakukan secara terencana, dan disiapkan secara matang. Keterlibatan TNI maupun POLRI adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, terutama di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, dan Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung dibakar massa yang tak terkendali. Selain terjadi sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia, hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan data bahwa dalam tragedi ini, 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan.
Keterlibatan pemerintah orde baru juga diungkapkan Komnas HAM seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini:
“Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.
Dokumen tersebut juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI bersama Alex Widya S. Diduga, Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo untuk melakukan penyerbuan. Seperti tercatat di dokumen itu, rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-Kongres Medan. Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000.” (http://id.wikipedia.org/wiki/peristiwa 27- Juli.htm)”.
Pemerintah orde baru pada peristiwa tersebut mencoba memanipulasi fakta sejarah dengan menjadikan para aktivis PRD sebagai kambing hitam yang menjadi dalang dari kerusuhan ini. Akibatnya beberapa aktivis PRD dijebloskan ke dalam penjara. Pemerintah dengan ini mencoba membentuk opini publik untuk menutupi keterlibatan mereka:
“Wayan Togog, Bilung, dan Koba ada di Jakarta bulan Juli lalu. Dan seperti Budiman Sudjatmiko serta yang lain, mereka juga terpanggil untuk berbicara di mimbar bebas jalan Diponegoro, di depan kantor PDI, saling memperkuat antara orang-orang yang melawan Suharto. Di situlah intel-intel mencatat dan merekam wajah mereka.” (Larung, 2002:183).
Setelah rezim orde baru tumbang proses hukum untuk menyelesaikan masalah ini juga terkesan angin-anginan. Beberapa tokoh militer yang dianggap terlibat pun divonis bebas oleh pengadilan. Tidak tuntasnya penyelesaian kasus ini adalah cermin penegakan hukum di Indonesia yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari sini masyarakat bisa melihat, bila sudah berhadapan dengan penguasa, hukum pun tidak bisa berbuat apa-apa. Peristiwa 27 Juli juga mencerminkan karakteristik kediktaktoran pemerintahan orde baru yang selalu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.
Pengungkapan Peristiwa 27 Juli 1996 Dalam Novel Larung Karya Ayu Utami
Label: Esai
Seksualitas Dalam Novel "Nayla" Karya Djenar Maesa Ayu
1. Seksualitas Remaja
Masa remaja adalah masa peralihan bagi seorang manusia, dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini adalah masa yang rentan dengan konflik psikologis, karena manusia mengalami proses pembentukan diri, dan pencarian identitas dirinya. Di tengah situasi tersebut kepribadian manusia menjadi labil, mudah menerima berbagai bentuk pengaruh. Usia Remaja adalah 12 hingga 21 tahun. Di usia ini seksualitas mulai menampakkan eksistensinya secara penuh. Aktifitas reproduksi memasuki fungsinya yang maksimal, dan lawan jenis mulai memberikan daya tarik yang utuh. Hubungan dengan lawan jenis menjadi lebih matang dari sebelumnya.
 Dijelaskan Ratna Eliyawati, pada saat ini juga remaja sudah mampu menghayati makna rangsangan seksual terlepas dari apakah rangsangan seksual tersebut berasal dari proses persentuhan hati dengan lawan jenis (sosio-erolik) atau akibat berfantasi (auto-erotik), (http://yudhim.blogspot.com)
Dijelaskan Ratna Eliyawati, pada saat ini juga remaja sudah mampu menghayati makna rangsangan seksual terlepas dari apakah rangsangan seksual tersebut berasal dari proses persentuhan hati dengan lawan jenis (sosio-erolik) atau akibat berfantasi (auto-erotik), (http://yudhim.blogspot.com) Para ahli psikologi mengatakan pada masa ini informasi yang benar tentang masalah seksualitas penting untuk diberikan, karena saat periode remaja rasa ingin tahu kita mengenai seksualitas sedang membumbung tinggi. Jika tidak mendapatkan informasi yang benar, remaja akan akan mencari sendiri informasi-informasi di luar yang bisa saja keliru, yang dapat berpengaruh pada kejiwaannya. Pendapat sebagian besar masyarakat yang mengatakan bahwa masalah seksualitas adalah hal alamiah yang akan diketahui dengan sendirinya ketika seseorang melakukan pernikahan harus segera dikikis. Terjadinya kasus aborsi, hamil di luar nikah atau penyakit kelamin adalah akibat dari kurangnya informasi mengenai seksualitas terhadap anak muda. Peran orangtua untuk pemberian informasi tersebut dalam hal ini sangat penting.
Para ahli psikologi mengatakan pada masa ini informasi yang benar tentang masalah seksualitas penting untuk diberikan, karena saat periode remaja rasa ingin tahu kita mengenai seksualitas sedang membumbung tinggi. Jika tidak mendapatkan informasi yang benar, remaja akan akan mencari sendiri informasi-informasi di luar yang bisa saja keliru, yang dapat berpengaruh pada kejiwaannya. Pendapat sebagian besar masyarakat yang mengatakan bahwa masalah seksualitas adalah hal alamiah yang akan diketahui dengan sendirinya ketika seseorang melakukan pernikahan harus segera dikikis. Terjadinya kasus aborsi, hamil di luar nikah atau penyakit kelamin adalah akibat dari kurangnya informasi mengenai seksualitas terhadap anak muda. Peran orangtua untuk pemberian informasi tersebut dalam hal ini sangat penting.Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar remaja kita tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, seringkali remaja sangat tidak matang untuk melakukan hubungan seksual terlebih lagi jika harus menanggung resiko dari hubungan seksual tersebut (http://agoesramdhanie.wordpress.com/2008/12/19/psikologi-pendidikan-seks-pada-remaja).
Nayla, tokoh utama dalam novel ini adalah seorang perempuan yang melewati masa kecil hingga remaja dengan berbagai pengalaman pahit. Masa tersebut ia lewati dengan tekanan batin dan tekanan psikologis yang ia alami di lingkungan sekitarnya. Sejak kecil ibunya sering menusukkan peniti ke selangkangannya setiap kali Nayla ngompol di celana. Ia tak mengerti mengapa ibunya melakukan cara-cara seperti itu untuk menghukumnya. Padahal, Nayla mengharapkan ibunya memperlakukannya layaknya ibu-ibu lain memperlakukan anak mereka. Lahir dari keluarga broken home membuat Nayla berusaha mencari kebahagiaannya tanpa bantuan orang lain. Di usia yang rentan seperti itu Nayla tak mempunyai pegangan ketika ia tak mampu berdiri sendiri. Di tengah situasi psikologis yang sangat labil, Nayla berkenalan dengan Juli, seorang perempuan yang sama-sama bekerja dengannya di sebuah diskotek. Nayla bekerja sebagai juru lampu, dan Juli sebagai juru musik. Juli adalah seorang wanita yang memiliki sisi kelaki-lakian dalam dirinya. Ia seorang lesbian, dan dengan Juli Nayla seperti mendapatkan seorang sahabat sejati. Ia merasa mendapatkan kasih sayang yang tidak ia dapatkan dari ibunya:
“Tak pernah saya mencintai satupun laki-laki. Tidak sebagai ayah, tidak sebagai kekasih. Saya pernah belajar mencintai perempuan. Mencintai Ibu. Tapi sayangnya, Ibu tak pernah belajar mencintai saya. Ia lebih senang belajar mencintai kekasih-kekasihnya. Bersama Juli, saya merasakan kehangatan kasih yang pernah ingin saya berikan kepada Ibu” (2005:5).
Lewat kutipan tersebut kita bisa mendapatkan kesan bahwa, problem psikologis seseorang dapat mempengaruhi kehidupan seksualnya. Karena hidup tanpa mendapatkan kasih sayang dari sosok ayah, Nayla dikatakan tidak bisa mencintai laki-laki. Bersama Juli, Nayla merasakan kenyamanan dan tempat berlabuh dari tekanan yang terus menerus ia terima. Bahkan, ia merasa cemburu ketika melihat Juli bermesraan dengan kekasihnya.
Tekanan psikologis dalam dirinya semakin bertambah ketika ia secara paksa dimasukkan dalam rumah perawatan anak nakal dan narkotika. Nayla tidak pernah mengerti kenapa dirinya dimasukkan ke sana. Ibu memasukkan ia ke sana karena mendapati Nayla mabuk dan dipengaruhi obat-obatan terlarang. Padahal Nayla hanya mencoba mencari ketenangan dengan teman-temannya. Terjeblos di tempat itu bagi Nayla seperti keluar dari satu neraka dan masuk ke neraka lainnya. Di sana ia terpaksa menjalani rutinitas-rutinitas yang sedikitpun tak memberi pengaruh positif dalam dirinya:
“Pada saat berada di kamar tak ada yang diperbolehkan berbicara. Tak boleh melakukan aktifitas apa pun. Tampaknya mereka tak diperbolehkan berinteraksi dengan dunia luar. Tak boleh ada kertas. Tak ada pensil. Tak ada televisi. Tak ada majalah. Bahkan sendok garpu pun tak disediakan. Mereka menyantap makanan berkuah sekali pun dengan tangan. Tak ada kehidupan. Selain mematuhi peraturan.” (2005:15).
Nayla semakin merasa tersiksa, ia pun akhirnya memutuskan melarikan diri dari rumah perawatan tersebut. Tapi setelah itu, pengalaman hidup kelam Nayla justru semakin bertambah ketika ia berurusan dengan polisi:
“Kepala Nayla terjungkal ke belakang ketika seorang polisi yang sedang berdiri menjambak rambutnya.
“Kecil-kecil sok mau jadi preman kamu, ya! Ngapain jalan-jalan bawa senjata tajam?!”
“Bukan punya saya, Pak!”
“Eh, perek kecil! Temen kamu udah ngaku kalo itu senjata tajamnya dia. Jadi kamu jangan bohong!”
Nayla melirik ke arah Luna yang sedang diinterogasi di meja sebelah. Luna memberi kode supaya tidak mengaku.” (2005:73).
Di usianya yang ke empat belas tahun Nayla begitu terobsesi untuk bisa merasakan cinta. Rasa cinta baginya seolah menjadi sesuatu yang amat langka sejak kecil. Pengalaman-pengalaman pahit membuatnya ingin mandiri dan merasa benci ketika Juli memperlakukannya seperti seorang remaja yang harus dilindungi:
“Saya sering kesal setiap kali Juli bersikap ingin melindungi. Di matanya, saya hanyalah perempuan berumur empat belas tahun yang frustasi dan sedang mencari jati diri. Padahal saya mampu mencinta dan bercinta. Saya ingin belajar merasa. Tapi saya tak ingin memberi cinta saya kepada orang-orang yang tak semestinya menerima. Lebih baik saya memilih mencintai Juli ketimbang laki-laki yang menginginkan selaput dara saja” (2005:6).
 Pengalaman traumatik membuat Nayla selalu curiga dan tidak mudah mempercayai orang lain. Meski, ia ingin sekali mencintai maupun dicintai oleh seseorang, dibutuhkan sebuah proses untuk meyakinkan Nayla bahwa orang tersebut pantas ia cintai. Baik Nayla maupun Juli merupakan tokoh yang oleh pengarang digambarkan sebagai sosok yang membenci laki-laki. Mereka menganggap laki-laki hanyalah mahluk berpikiran kerdil yang di otaknya cuma ada senggama belaka. Masalah seksualitas perempuan dalam novel ini tampak bersumber pada laki-laki. Sebuah bentuk perlawanan yang menyebabkan sosok lelaki menjadi unsur yang tidak penting dan tidak perlu dikaitkan dengan eksistensi perempuan. Tokoh-tokoh perempuan bergelut mencari kebahagiaan tanpa melibatkan lelaki sebagai bagian untuk memperoleh semua itu:
Pengalaman traumatik membuat Nayla selalu curiga dan tidak mudah mempercayai orang lain. Meski, ia ingin sekali mencintai maupun dicintai oleh seseorang, dibutuhkan sebuah proses untuk meyakinkan Nayla bahwa orang tersebut pantas ia cintai. Baik Nayla maupun Juli merupakan tokoh yang oleh pengarang digambarkan sebagai sosok yang membenci laki-laki. Mereka menganggap laki-laki hanyalah mahluk berpikiran kerdil yang di otaknya cuma ada senggama belaka. Masalah seksualitas perempuan dalam novel ini tampak bersumber pada laki-laki. Sebuah bentuk perlawanan yang menyebabkan sosok lelaki menjadi unsur yang tidak penting dan tidak perlu dikaitkan dengan eksistensi perempuan. Tokoh-tokoh perempuan bergelut mencari kebahagiaan tanpa melibatkan lelaki sebagai bagian untuk memperoleh semua itu:“Otak laki-laki memang kerdil. Senggama bagi mereka hanya berkisar di seputar kekuatan otot Vagina,” kata Juli.
Saya sependapat dengannya. Karena itu saya tak terlalu bangga ketika banyak tamu laki-laki dan juru musik yang lain mengaku tergila-gila pada saya. Mereka berlomba-lomba mendapatkan tubuh saya. Mereka pasti bangga jika berhasil merobek selaput dara saya. Bodoh. Mereka mengira saya perawan. Padahal hati saya yang perawan, bukan vagina saya. Meskipun usia saya masih sangat muda” (2005:5).
Secara implisit tergambar rasa sinis Nayla bahwa laki-laki hanya melihat perempuan untuk urusan fisik semata. Lelaki di matanya tidak pernah memusingkan perasaan perempuan. Ia menganggap tidak ada gunanya memberikan cinta kepada orang yang tidak mengerti perasaan perempuan. Baginya hanya Juli yang mengerti isi hatinya. Bila dilihat lebih jauh sesungguhnya akar dari permasalahan Nayla dan ibunya terletak pada ayahnya.
Masa remaja adalah masa di mana setiap manusia harusnya memperoleh pendidikan seks secara benar, baik mengenai peranan seks, fungsinya, serta hubungannya dengan masalah moral, etika, ataupun agama. Telah dipaparkan bahwa untuk urusan yang satu ini orangtua mempunyai peran yang sangat vital. Namun, semua itu tidak didapatkan Nayla. Hal ini menyebabkan dirinya bertindak sesuai dengan respon yang ia dapatkan dalam lingkungan sosialnya. Selain pendidikan secara langsung, sikap orangtua terhadap seksualitas juga berpengaruh terhadap sikap seksual seorang anak. Ibu Nayla adalah sosok berkarakter keras yang memiliki dendam terhadap lelaki. Ia mendidik Nayla seorang diri, karena suaminya meninggalkannya dengan alasan bahwa Nayla bukanlah anak dari benihnya. Rasa dendam terhadap suaminya itu berimbas pada perkembangan psikologi Nayla. Gadis itu dididik secara keras agar kelak tidak menjadi korban kesia-siaan lelaki.
2. Homoseksualitas
Homoseksualitas novel “Nayla” ditampilkan lewat unsur lesbian. Sama seperti kaum gay, pada masyarakat Indonesia lesbian juga belum mendapatkan kedudukan sosial yang sesuai sebagai manusia. Keberadaan mereka juga masih terkesan samar, mengingat kaum lesbian memiliki interaksi sosial tak seaktif kaum gay. Sesuai dengan karakteristiknya, bagaimanapun lelaki memiliki perilaku seksual lebih agresif daripada perempuan. Lesbian yang melakukan ‘coming out’ juga sangat minim, jika boleh dibilang tidak ada sama sekali. Untuk bisa mengidentifikasi mereka secara langsung juga sangat sulit, berbeda dengan gay yang ciri-cirinya bisa terlihat lewat pembawaan atau cara berbusana. Sedangkan perempuan yang memiliki ciri-ciri kelaki-lakian atau tomboi tidak bisa langsung divonis sebagai lesbian.
Bila melihat sejarah, citra buruk lesbian di Indonesia mulai terkonstruksi sejak masa organisasi wanita, Gerwani masih berkiprah. Citra gerwani yang kejam, melakukan praktek prostitusi dan berhubungan sesama jenis berpengaruh pada citra kaum lesbian secara keseluruhan. Tetapi, sesungguhnya jika kita coba mengkaji kembali sumber-sumber sejarah, yang terjadi di tubuh Gerwani bertolak belakang dengan stigma seperti itu. Dijelaskan Oryza Sativa bahwa:
 “Konstruksi tersebut adalah perjalanan panjang yang muncul dari kombinasi: usaha untuk maju dan sejajar dengan lelaki serta tidak menelan mentah-mentah konsep kodrat dan dinamika politik Indonesia. Namun dengan beraneka alasan, tujuan-tujuan itu malah menjadi semacam bumerang yang dipicu oleh faktor eksternal yakni rezim Orde Baru” (http://sepocikopi.blogspot.com).
“Konstruksi tersebut adalah perjalanan panjang yang muncul dari kombinasi: usaha untuk maju dan sejajar dengan lelaki serta tidak menelan mentah-mentah konsep kodrat dan dinamika politik Indonesia. Namun dengan beraneka alasan, tujuan-tujuan itu malah menjadi semacam bumerang yang dipicu oleh faktor eksternal yakni rezim Orde Baru” (http://sepocikopi.blogspot.com).Rezim Orde Baru yang terkenal dengan sifat feodalismenya, dengan tujuan-tujuan politis memanipulasi perjuangan kaum Gerwani sebagai gerakan negatif di mata masyarakat. Manipulasi tersebut berkaitan dengan ideologi yang dipegang organisasi ini, yang menurut pemerintahan Orde Baru dapat mengancam stabilitas negara. Konstruksi moral yang dibangun terus berlaku dan masih dirasakan sampai saat ini.
Di dalam novel “Nayla” terdapat dua tokoh dengan tipikal invert berbeda. Juli dan Nayla. Tidak dijelaskan latar belakang mengapa Juli menjadi lesbian. Ia digambarkan telah memiliki orientasi seksual ke sesama jenis sejak masih remaja:
“Saya memperhatikan Juli. Perawakan dan sikap Juli tak ubahnya seorang laki-laki. Ia memang pencinta sesama jenis. Tapi kelainannya bukan faktor genetis. Keluarganya normal-normal saja, akunya. Normal dalam pengertian, bukan pencinta sesama jenisnya. Tapi Juli mempunyai karisma. Banyak tamu perempuan tergila-gila padanya. Yang laki-laki pun tak jarang ingin menaklukkannya. Pasti enak meniduri perawan, pikir mereka. Padahal sebagai sahabatnya, saya tahu Juli sudah tidak perawan. Semenjak remaja ia suka memasukkan benda-benda ke dalam vaginanya sambil membayangkan perempuan yang ia idamkan. Sekarang pun dengan kekasihnya yang seorang model mereka sering bercinta dengan cara saling memasuki vagina satu sama lain dengan jari mereka” (2005:4-5).
Melalui kutipan tersebut kita bisa mendapat kesan bahwa Juli adalah perempuan yang masuk dalam kategori absolutely inverted. Kesan itu diperkuat karena di dalam novel tidak dijelaskan apakah dirinya menyukai, atau pernah menjalin hubungan dengan lelaki.
Sedangkan Nayla termasuk dalam kategori psychosexually hermaphroditic, atau seorang biseksual. Sebelumnya Nayla adalah seorang perempuan yang mempunyai orientasi seks normal. Karakter invertnya muncul akibat adanya konflik psikologi yang mempengaruhi kejiwaannya. Perkenalannya dengan Juli menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses peralihan tersebut. Dengan Juli ia merasakan kasih sayang dan rasa nyaman yang tidak ia peroleh dari kedua orangtuanya. Karena sejak kecil sangat jarang merasakan kasih sayang seperti itu, cinta Nayla kepada Juli menjadi berlebihan. Hal ini disebabkan oleh perasaan takut kehilangan akan perlakuan dan rasa nyaman yang jarang ia dapati tersebut. Bahkan, ia memutuskan menjadikan Juli sebagai kekasihnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Perilaku invert Nayla lebih cenderung bersifat emosional daripada seksual. Ketika hubungannya dengan Juli berakhir, dampaknya dalam diri Nayla terasa begitu besar:
“Akhirnya Juli pergi. Kembali, saya sendiri. Tak pernah saya bayangkan akan merasa sangat kehilangan seperti ini walaupun secara moril materiil saya sudah mempersiapkan diri” (2005:104).
Selain menjalin hubungan dengan Juli, Nayla juga berhubungan dengan laki-laki pengunjung diskotek yang tertarik padanya. Akan tetapi, dengan mereka Nayla tidak pernah mendapatkan kepuasan seperti yang ia dapatkan ketika berhubungan seks dengan Juli. Ia lebih menikmati ketika melihat semua laki-laki itu berada di bawah cengkramannya, ketika mereka semua mengemis ingin mendapatkannya. Nayla merasa senang karena ia merasa bisa memperbudak kaum lelaki.
Label: Esai
Biseksualitas Dalam Dwilogi Novel "Saman"-"Larung" Karya Ayu Utami
 Sama halnya dengan lesbian, kaum biseksual atau psychosexually hermaphroditic dari kalangan perempuan juga sangat jarang kita temui. Kalaupun ada, mereka hanya ada terbatas dalam lingkungan pergaulan masyarakat hedonis yang identik dengan kehidupan malam. Di dalam pergaulan seperti itu hubungan heteroseksual adalah sesuatu yang sudah sangat biasa, bahkan mungkin membosankan. Keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, menjadi dasar kuat merebaknya gaya hidup seks non heteroseksual.
Sama halnya dengan lesbian, kaum biseksual atau psychosexually hermaphroditic dari kalangan perempuan juga sangat jarang kita temui. Kalaupun ada, mereka hanya ada terbatas dalam lingkungan pergaulan masyarakat hedonis yang identik dengan kehidupan malam. Di dalam pergaulan seperti itu hubungan heteroseksual adalah sesuatu yang sudah sangat biasa, bahkan mungkin membosankan. Keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, menjadi dasar kuat merebaknya gaya hidup seks non heteroseksual.
Sebuah penelitian mengatakan, orientasi biseksual cenderung terdapat pada perempuan. Tetapi, seperti yang dikatakan Lisa Diamond, (http://www.sinarharapan.co.id/iptek/kesehatan/2003/0627/kes2.html), orientasi seksual sesungguhnya merupakan sebuah fenomena yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Orientasi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai variasi emosi dan faktor fisik, terutama pada perempuan. Hal tersebut pula yang menyebabkan mengapa kecenderungan biseksual pada kebanyakan perempuan tidak tampak ke permukaan, dan hanya menemukan kebebasan eksistensinya di dalam lingkungan-lingkungan tertentu seperti dalam gaya hidup kehidupan malam kaum hedonis. Padahal perempuan memiliki orientasi seks jauh lebih kaya daripada lelaki.
Salah satu sahabat dekat Laila selain Yasmin adalah Shakuntala. Seorang perempuan bertubuh semampai yang juga seorang penari. Identitas Shakuntala sebagai seorang biseks langsung dipaparkan pengarang pada penggalan pertama ketika cerita memaparkan narasi tentang dirinya:
“Namaku Shakuntala. Ayah dan kakak-perempuanku menyebutku sundal.
Sebab aku telah tidur dengan beberapa lelaki dan beberapa perempuan. Meski tidak menarik bayaran. Kakak dan ayahku tidak menghormatiku. Aku tidak menghormati mereka.” (Saman, 2002:115).
Lewat kutipan yang sangat eksplisit tersebut langsung diketahui latar belakang kehidupan sang tokoh, dan permasalahan yang ia alami akibat dari perilaku seksualnya. Kepribadian Shakuntala dan kecenderungan seksual ganda yang dimilikinya juga dilukiskan pengarang lewat ciri khas berikut ini:
“Aku mahir merubah suaraku. Kadang aku ini kera Sugriwa dengan geram egresif maupun ingresif dalam trakhea. Kali lain aku adalah cangik yang suaranya yang klemak-klemek seperti kulit ketiaknya yang lembek. Ketika remaja aku selalu menari sebagai Arjuna dalam Wayang orang, dan gadis-gadis memujaku sebab tanpa sadar mereka tak menemukan sisa-sisa femininiti dalam diriku. Tapi aku juga Drupadi, yang memurubkan gairah pada kelima pandawa.” (Saman, 2002:117-118).
Lewat suara dan tariannya Shakuntala digambarkan memiliki sisi feminim maupun sisi maskulin.
Hampir sama dengan Laila, Shakuntala hidup di bawah didikan orangtua yang mempunyai standarisasi tertentu tentang bagaimana tingkah laku perempuan yang dianggap baik. Sejak kecil ia tidak merasa nyaman dengan pandangan orangtuanya mengenai pembagian etika lelaki dan perempuan. Seperti wewejang ayahnya tentang cinta yang dinasehatkan padanya berikut ini:
“Pertama. Hanya lelaki yang boleh menghampiri perempuan. Perempuan yang mengejar-ngejar lelaki pastilah sundal. Kedua. Perempuan akan memberikan tubuhnya pada lelaki yang pantas, dan lelaki itu akan menghidupinya dengan hartanya. Itu dinamakan perkawinan. Kelak, ketika dewasa, aku menganggapnya persundalan yang hipokrit.” (Saman, 2002:120-121).
Nasehat ayahnya di atas adalah nasehat orangtua konservatif pada umumnya. Cara pandang seperti itu masih terus berkembang karena diwariskan turun-temurun. Setiap anak diharuskan untuk patuh terhadap orangtua, bagi yang melawan dianggap anak durhaka dan tak tahu diuntung. Sistem kepatuhan tanpa ada proses penyaringan inilah yang menyebabkan cara pandang ini terus berkembang. Dari orang tua ke anak, dan dari anak menyebar ke lingkungan pergaulan sosial. Di dalam diri Shakuntala terdapat keinginan untuk memberontak, tidak hanya ayahnya, ibunya memiliki perspektif yang tak jauh beda:
“Ibuku berkata, aku tak akan retak selama aku memelihara keperawananku. Aku terheran, bagaimana kurawat sesuatu yang aku belum punya? Ia memberitahu bahwa di antara kedua kakiku, ada tiga lubang. Jangan pernah kau sentuh yang tengah, sebab di situlah ia tersimpan. Kemudian hari kutahu, dan aku agak kecewa, bahwa ternyata bukan cuma aku saja yang sebenarnya istimewa. Semua anak perempuan sama saja. Mereka mungkin saja teko, cawan, piring, atau sendok sup, tetapi semuanya porselin. Sedangkan anak laki-laki? Mereka adalah gading: tak ada yang tak retak. Kelak, ketika dewasa, kutahu mereka juga daging.” (Saman, 2002:124).
Shakuntala merasa ada yang janggal dengan kodrat yang diberikan kepada wanita, di sana terdapat diskriminasi. Keperawanan hanya boleh diberikan kepada suami, tanpa harus menuntut sang suami menyerahkan hal yang sama. Doktrin tersebut tertanam ke dalam pikiran sampai ke alam bawah sadar. Hal ini yang menyebabkan perempuan merasa sakit ketika berhubungan seks untuk pertama kali, karena yang ada dalam benaknya adalah rasa takut ketimbang menikmati senggama.
Shakuntala adalah sosok yang memiliki kehidupan unik. Ia memiliki jiwa sebagai seorang seniman yang menikmati keindahan menurut tafsirannya sendiri. Kapan ia menyadari ada sisi kelaki-lakian dalam dirinya dan apa penyebabnya juga bagai misteri:
“Tetapi lelaki dalam diriku datang suatu hari. Tak ada yang memberi tahu dan ia tak memperkenalkan diri, tapi kutahu dia adalah diriku laki-laki. Ia muncul sejak usiaku amat muda, ketika itu aku menari baling-baling.” (Larung, 2002:133).
Sosok Shakuntala oleh pengarang dijadikan sebagai wujud metaforis dari jiwa manusia dengan dua dimensinya. Lelaki dan perempuan. Pembagian tersebut tidak hanya sebatas pada jenis kelamin yang dimiliki, tapi memiliki makna lebih di luar hal-hal fisik. Daya tarik kepribadian atau karisma, dan lain-lain. Laila, sahabatnya bisa secara spesifik merasakan unsur kelaki-kelakian dalam diri Shakuntala ketika Shakuntala mempertunjukan kemampuan menarinya yang bisa menampakkan dua kepribadian sekaligus:
“Lalu musik berhenti. Telah satu jam. Telah satu jam kami berdansa. Kami saling melepas pelukan. Saya melihat ia berkeringat. Ia mencopot kamejanya begitu saja seperti seorang lelaki menanggalkan pakaiannya yang telah basah. Dan tengkurap. Saya melihat otot punggungnya. Titik-titik peluh. Ia berbalik. Lalu saya menemukan wajah saya telah bersandar pada siku lehernya. Dan saya menangis. Sebab sesungguhnya saya tahu saya terluka oleh sikap Sihar. Sebab kini saya tak tahu lagi siapa dia. Apakah Tala apakah Saman apakah Sihar. Hangat nafasnya terasa. Cahaya rendah.” (Larung, 2002:131-132).
 Laila yang baru saja mengalami kekecawaan terhadap Sihar terhipnotis oleh daya tarik yang ditunjukkan Shakuntala lewat kemampuan menarinya, begitu terhipnotis hingga ia pun secara alamiah larut dalam pelukan sahabatnya itu. Ia melepaskan hasrat seksual dengannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan, bahwa pada kaum perempuan, pengalaman atraksi seks tidak tergantung pada gen pasangannya saja, tapi juga terpengaruh oleh segala sesuatu di sekitarnya. Itulah yang dialami Laila, atraksi seksualnya dengan Shakuntala lebih dipengaruhi oleh faktor situasi yang mereka berdua lewati. Jadi, meski Laila memiliki orientasi seks normal, ia bisa saja mendapatkan kenikmatan seks dengan Shakuntala.
Laila yang baru saja mengalami kekecawaan terhadap Sihar terhipnotis oleh daya tarik yang ditunjukkan Shakuntala lewat kemampuan menarinya, begitu terhipnotis hingga ia pun secara alamiah larut dalam pelukan sahabatnya itu. Ia melepaskan hasrat seksual dengannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan, bahwa pada kaum perempuan, pengalaman atraksi seks tidak tergantung pada gen pasangannya saja, tapi juga terpengaruh oleh segala sesuatu di sekitarnya. Itulah yang dialami Laila, atraksi seksualnya dengan Shakuntala lebih dipengaruhi oleh faktor situasi yang mereka berdua lewati. Jadi, meski Laila memiliki orientasi seks normal, ia bisa saja mendapatkan kenikmatan seks dengan Shakuntala.Label: Esai
Unsur Perselingkuhan Dalam Dwilogi novel “Saman”-“Larung” Karya Ayu Utami
 “Saman” dan “Larung” adalah novel dengan tokoh-tokoh perempuan yang melakukan perlawanan terhadap norma-norma mapan yang telah ada. Bagi mereka, sistem kebudayaan dan konstruksi moral yang ada di dalam masyarakat sangat mengungkung kebebasan perempuan. Lembaga perkawinan, masalah keperawanan, adalah beberapa contoh di antaranya. Tidak ada keadilan gender di dalam semua itu. Dengan tokoh-tokoh seperti itu, maka perselingkuhan adalah unsur paling dominan yang terdapat dalam kedua novel ini.
“Saman” dan “Larung” adalah novel dengan tokoh-tokoh perempuan yang melakukan perlawanan terhadap norma-norma mapan yang telah ada. Bagi mereka, sistem kebudayaan dan konstruksi moral yang ada di dalam masyarakat sangat mengungkung kebebasan perempuan. Lembaga perkawinan, masalah keperawanan, adalah beberapa contoh di antaranya. Tidak ada keadilan gender di dalam semua itu. Dengan tokoh-tokoh seperti itu, maka perselingkuhan adalah unsur paling dominan yang terdapat dalam kedua novel ini.
Di dalam Supernova “Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh”, perselingkuhan menjadi konflik yang krusial karena yang berselingkuh adalah tokoh perempuan. Masyarakat patriarkal menganggap laki-laki yang berselingkuh adalah laki-laki kurang ajar, tidak berperasaan, namun di satu sisi masih terselip rasa maaf karena perselingkuhan yang dilakukan lelaki dianggap sesuatu yang masih bisa diterima. Sedangkan perempuan yang berselingkuh dianggap perempuan hina, tak bermoral, tidak bertanggungjawab, bahkan kadang dianggap pelacur.
Laila Gagarina adalah seorang fotografer yang jatuh cinta kepada Sihar Situmorang, seorang insinyur perminyakan yang telah beristri. Laila begitu terobsesi dengan Sihar, ia sama sekali tak mempedulikan meskipun ia akan sulit mendapatkan lelaki itu sepenuhnya karena lembaga perkawinan yang mengikat Sihar. Ia juga tak mengambil pusing dengan dampak sosial yang akan diterimanya karena mengejar-ngejar suami orang. Ia hanya ingin bahagia sebagai perempuan dengan memperjuangkan rasa cintanya kepada Sihar. Di dalam masyarakat umum, standar nilai yang berlaku di kalangan perempuan, berhubungan dengan lelaki adalah dalam rangka mengejar sebuah ikatan resmi, kubutuhan ekonomi tercukupi, atau bisa juga urusan seks. Sosok Laila bertolak belakang dengan motivasi seperti itu:
“Jadi, apa sebetulnya yang kamu cari? Perkawinan bukan, seks bukan.”
“Aku cuma pingin sama-sama dia.”
“Laila, kalau kamu kencan dengan dia di sini, kamu pasti akan begituan, lho! Kamu sudah siap?”
“Enggak, enggak tahu...”
“Dia pasti minta. Kamu mau gimana?”
“Aku cuma pingin sama-sama dia. Aku capek menahan diri.” (Saman, 2002:145).
Terjadi perubahan perspektif tentang masalah seksualitas dan gender antara Laila remaja dan Laila dewasa. Waktu masih remaja Laila sangat membenci laki-laki, ia menganggap laki-laki lah sumber masalah bagi perempuan:
“Apa salah laki-laki?
Jawab Laila: sebab mereka mengkhianati wanita. Mereka cuma menginginkan keperawanan, dan akan pergi setelah si wanita menyerahkan kesucian.” (Saman, 2002:148).
Laila remaja adalah perempuan yang bersikap berdasarkan perspektif yang terdapat dalam sistem nilai di lingkungan sekitarnya. Berasal dari keluarga Minang-Sunda, yang masih memegang nilai-nilai tradisi, sangat mempengaruhi sikap hidupnya. Artinya, belum ada kesadaran untuk memberontak akan sistem nilai tersebut. Cara pandangnya berubah ketika ia menemukan cinta pertamanya:
“Dia jatuh cinta pertama kali pada Wisanggeni, dengan demikian ia sendiri membatalkan lelaki sebagai penjahat. Waktu itu pemuda itu mahasiswa seminari yang ditugaskan membimbing rekoleksi tentang kesadaran sosial di SMP kami. Dan terbukti lelaki itu tidak menginginkan keperawanan.” (Saman, 2002:149-150).
Laila sendiri tidak mempunyai pacar. Kendala yang akan menghambat hubungannya dengan Sihar adalah kedua orangtuanya, yang sudah pasti tak menginginkan anak gadisnya berhubungan dengan pria yang sudah kawin. Tapi, Laila sama sekali tidak mempedulikan masalah perkawinan.
Hubungan Laila dan Sihar meskipun bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama mengandung sesuatu yang paradoks. Ada semacam nilai yang masih dipegang Laila sebagai perempuan, yang bisa disebabkan beban moralnya terhadap orangtua. Meski, telah beberapa kali bercumbu dengan Sihar, Laila masih menjaga keperawanannya:
“Di perjalanan pulang dia bilang, sebaiknya kita tak usah berkencan lagi (saya tidak menyangka). “Saya sudah punya istri.”
Saya menjawab, saya tak punya pacar, tetapi punya orangtua.
“Kamu tidak sendiri, saya juga berdosa.”
Ia membalas, bukan itu persoalannya. “Orang yang sudah kawin, tidak bisa tidak begitu.”
Saya mengerti. Meskipun masih perawan.” (Saman, 2002:4).
Laki-laki yang memutuskan berselingkuh biasanya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kepuasan yang tak lagi ia rasakan bersama istrinya. Kepuasan itu bisa berupa kepuasan seks, kasih sayang, dan lain sebagainya. Namun, dalam hal ini meskipun hanya sebagai pasangan selingkuh, Sihar menghormati Laila, walau pun di satu sisi ia ingin berhubungan seks dengan perempuan itu, ia tak memaksa Laila menyerahkan keperawanannya. Mereka pun menggunakan cara lain (selain senggama) untuk memuaskan hasrat seksual keduanya.
Ketika mengetahui Sihar mendapatkan tugas perusahan untuk berangkat ke Amerika, Laila memutuskan untuk menyusulnya. Di negara ini Laila merasakan suasana yang berbeda. Kendala-kendala yang menghambat hubungannya dengan Sihar terasa seperti hilang. Di sini ia merasakan kebebasan yang tak didapatkan sebelumnya. Bahkan, kali ini ia berangan-angan untuk menyerahkan keperawanannya kepada lelaki itu:
“Dia akan terheran dan bertanya, dari mana kini saya mendapat keberanian itu. Juga dari teman-teman? Saya akan katakan, kita ini seperti burung yang bermigrasi ke musim kawin. Sihar, umurku sudah tiga puluh. Dan kita di New York. Beribu-ribu mil dari Jakarta. Tak ada orangtua, tak ada istri. Tak ada dosa. Kecuali pada Tuhan, barangkali. Tapi kita bisa kawin sebentar, lalu bercerai. Tak ada yang perlu ditangisi. Bukankah kita saling mencintai? Atau pernah saling mencintai? Apakah Tuhan memerintahkan lelaki dan perempuan untuk mencintai ketika mereka kawin? Rasanya tidak. (Saman, 2002:29-30).
Di sini kita bisa mendapatkan perbedaan kondisi dalam dua kebudayaan yang berbeda, yang bisa mempengaruhi sikap seseorang. Ketika berpindah ke lain tempat yang memiliki kultur yang berbeda, yang menjunjung tinggi kebebasan manusia, terjadi perubahan sikap pada diri Laila. Laila yang sebelumnya hati-hati dalam melakukan hubungan terlalu jauh dengan Sihar, kini merasa dirinya terlepas bagaikan seekor burung. Sebelumnya, ketika bercumbu dengan Sihar, meski tetap menjaga keperawanannya, Laila merasa telah berdosa. Karena ia masih berada di bawah aturan sistem nilai yang berlaku di Indonesia. Tetapi, kini situasinya menjadi lain:
“Setelah itu, Sayang, kita tertidur. Dan ketika terbangun, kita begitu bahagia. Sebab ternyata kita tidak berdosa. Meskipun saya tak lagi perawan.” (Saman, 2002:30). Laila tidak lagi memusingkan masalah keperawanannya. Karena di Amerika, orang sama sekali tidak mempedulikan apakah perempuan masih perawan atau tidak, dan status pernikahan juga tidak terlalu penting di sini. Laila telah membayangkan bagaimana ia akan mendapatkan kebebasan untuk mendapatkan Sihar tanpa ada halangan.
Laila tidak lagi memusingkan masalah keperawanannya. Karena di Amerika, orang sama sekali tidak mempedulikan apakah perempuan masih perawan atau tidak, dan status pernikahan juga tidak terlalu penting di sini. Laila telah membayangkan bagaimana ia akan mendapatkan kebebasan untuk mendapatkan Sihar tanpa ada halangan.
Akan tetapi, ia harus membuang jauh keinginannya itu. Ternyata Sihar datang ke Amerika bersama istrinya. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada diri Laila. Selama di sana pun Sihar tak pernah memberikan kabar, atau membuat janji untuk bertemu dengannya. Apa sesungguhnya motivasi Sihar untuk mengencani Laila menjadi tanda tanya besar bagi perempuan itu. Apakah Sihar benar-benar mencintainya? Namun, bagaimanapun sebagai kepala rumah tangga ia mempunyai beban dan tanggung jawab lain yang harus diprioritaskan? Ataukah ia hanya menganggap Laila sebagai selingan untuk mengisi kekosongan di waktu senggang. Tapi, nyatanya Laila akhirnya tidak lagi memusingkan masalah itu. Ia hanya memikirkan perasaannya sendiri, dan bagaimana agar ia bisa berkencan lagi dengan Sihar. Ada sebuah kenyataan ironi di dalam hubungan mereka. Dari sikap Sihar yang selalu menghindar, tidak memaksa Laila untuk melakukan senggama dengannya waktu di hotel, dan menyeret Laila pada sebuah ketidakpastian, secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Sihar adalah tipe laki-laki yang tidak terlalu memusingkan masalah keperawanan. Istrinya sebagai seorang janda beranak satu, semakin mempertegas hal itu. Sedangkan Laila, adalah perempuan yang begitu protektif dengan keperawanannya. Usaha protektif tersebut harusnya membuat Laila menjadi perempuan yang istimewa, sebab laki-laki pada umumnya mengincar keperawanan dari pasangannya. Namun, Laila Justru sebaliknya, ia terombang-ambing oleh rasa cintanya kepada laki-laki yang telah beristri.
Sikap setengah hati Sihar, membuat kebimbangan besar di dalam hati Laila. Kebimbangan yang akhirnya melahirkan keraguan. Ia sebelumnya begitu menggebu-gebu untuk bisa bercumbu dengan lelaki itu, sampai ia pun menyusul Sihar ke Amerika. Namun, di sana kesempatan itu tak kunjung datang karena keberadaan istri Sihar. Akan tetapi, keraguan tadi justru muncul setelah istrinya kembali ke Indonesia dan peluang melakukan selingkuh terbuka begitu lebar:
“Istrimu sudah pulang?”
“Udah.” “Kamu mau ke sini?”
“Memang kamu mau saya ke situ?”
“Laila, saya kan menelepon kamu,” “Tapi, kalau ke sini, kamu jangan menginap di staff house. Kita cari hotel.”
“Kenapa?”
“Nggak begitu enak aja.”
“Kalau saya di hotel, kamu sibuk training di staff house, kamu tak selalu bisa menengok saya, untuk apa saya ke sana?”
“Saya usahakan menengok kamu tiap sore.”
“Saya lihat dulu saya bisa apa tidak.”
Pembicaraan telepon dengannya tak pernah diakhiri oleh kecupan.” (Larung, 2002:127-128).
Pembicaraan tersebut mengindikasikan ketidakjelasan sikap Sihar, dan Laila pun merasa ia tidak terlalu dibutuhkan oleh lelaki itu. Ini merupakan ironi karena sebelumnya Laila bahkan tak menuntut Sihar untuk mencintainya. Terjadi perubahan sikap di dalam dirinya setelah ia melewati proses bersama Sihar. Obsesi Laila pada lelaki itu seolah mencapai titik antiklimaks.
Tokoh lain yang melakukan selingkuh dalam dwilogi “Saman”-“Larung” adalah Yasmin Moningka, seorang pengacara yang juga salah satu sahabat dekat Laila sejak masih kecil. Meski, telah menikah dengan Lukas Hadi, Yasmin melakukan hubungan gelap dengan Athanasius Wisanggeni atau Romo Wis, yang kemudian berganti nama menjadi Saman saat menjalani status buronan. Kasus perselingkuhan Yasmin dan Saman memiliki banyak persamaan dengan Ferre dan Rana dalam Supernova “Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh”. Di dalam konteks Yasmin, konflik moral yang ditonjolkan lebih kompleks karena Saman adalah seorang pastor. Yasmin berkutat dengan konflik batin dan sosial yang berhubungan dengan status perkawinannya. Sedangkan Saman berkutat dengan konflik aturan agama, yang mengharuskan ia sebagai pastor untuk hidup selibat.
Tetapi, di dalam novel “Saman” kondisi tersebut tidak ditonjolkan sebagai konflik utama dalam cerita. Saman lebih sibuk mengurusi pelariannya ke Amerika atas kasus tuduhan penghasutan. Sedangkan Yasmin, bersama teman-temannya membantu Saman dalam proses pelarian itu. Agak berbeda dengan novel Supernova “Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh”, Latar belakang dan status Ferre ataupun Rana menjadi konflik yang dominan di dalam cerita. Yasmin dan Saman melakukan hubungan intim yang pertama kali dengan tanpa beban:
“Namun, tanpa kupahami, akhirnya justru akulah yang menjadi seperti anak kecil: terbenam di dadanya yang kemudian terbuka, seperti bayi yang haus. Tubuh kami berhimpit. Gemetar, selesai sebelum mulai, seperti tak sempat mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi ia tak peduli, ia menggandengku ke kamar. Aku tak tahu bagaimana aku akhirnya melakukannya. Ketika usai aku menjadi begitu malu. Namun ada perasaan lega yang luar biasa sehingga aku terlelap.” (Saman, 2002:177).
Saman sendiri adalah seorang pelayan Tuhan yang memilki jiwa sosial tinggi. Ia juga terlibat dalam organisasi yang oleh pemerintah dianggap kiri. Keinginannya untuk turun langsung membantu permasalahan yang ada di dalam masyarakat begitu besar. Ia jenuh dengan segala aturan gereja dan hirarki organisasi yang membatasi ruang geraknya. Teguran pun disematkan padanya karena sering mengabaikan tugas parokial:
“Wis terdiam. Lalu ia meminta maaf. “Saya sama sekali tidak bermaksud menyepelekan pekerjaan gereja. Saya cuma tak bisa tidur setelah pergi ke dusun itu.” Ia ingin mengatakan, rasanya berdosa berbaring di kasur yang nyaman dan makan rantangan lezat yang dimasak ibu-ibu umat secara bergiliran. Bahkan rasanya berdosa jika hanya berdoa. Ia tak tahan melihat kemunduran yang menurut dia dapat diatasi dengan beberapa proposalnya. Dengan agak memelas ia memohon diberi kesempatan melakukan itu.” (Saman, 2002:81-82).
Sikap Saman adalah bentuk perlawanan terhadap tubuh organisasi gereja yang baginya terlalu sibuk mengurusi urusan internal, dan sangat sedikit memberikan perhatian langsung terhadap masalah-masalah masyarakat secara luas. Ketika ia melarikan diri dari Indonesia, ia mengundurkan diri dari segala aktifitas pastoral, dan lebih aktif dengan LSM yang memberi perhatian terhadap masalah-masalah sosial.
Kekecewaannya terhadap gereja serta perkenalannya dengan Yasmin membuat hidup Saman berubah. Ia mulai meragukan kebenaran-kebenaran yang selama ini ia yakini:
“Yasmin,
Aku tak tahu lagi apakah masih ada dosa.
Seks terlalu indah. Barangkali karena itu Tuhan begitu cemburu sehingga Ia menyuruh Musa merajam orang-orang yang berzinah?
Tetapi perempuan selalu disesah dengan lebih bergairah. Ke manakah pria yang bersetubuh dengan wanita yang dibawa orang-orang Farisi untuk dilempari batu di luar gerbang Yerusalem?
Aku mencintai kamu. Aku mencintai kamu.
Aku tidak ingin kamu dihukum.” (Saman, 2002:183-184).
Saman menyadari bahwa apa yang dilakukannya bersama Yasmin adalah dosa di mata agama. Tapi, sesuatu yang ia rasakan bersama perempuan itu memiliki kekuatan yang terlalu besar, dan akhirnya ia pun menyerah. Ia terjabak pada dilema antara harus menjalankan hidup selibat, dan mengetahui bahwa persetubuhan adalah sesuatu yang indah. Meski, di satu sisi ia juga masih merindukan kehidupannya yang dulu sebagai seorang yang hidup menahan diri dari segala nafsu. Baginya seks adalah sesuatu yang sukar untuk ditafsirkan, yang membuat dirinya terjebak dalam kebingungan, dan semua itu disebabkan oleh seorang perempuan bersuami bernama Yasmin. Ketika jarak memisahkan mereka, komunikasi pun terjalin lewat email. Bahkan, karena membaca surat-surat Yasmin, Saman sampai terangsang dan melakukan masturbasi. Yasmin pun tak bisa melupakan Saman hingga ia terkena apa yang dinamakan aloerotisme:
“Saman,
Aku terkena aloerotisme. Bersetubuh dengan Lukas tetapi membayangkan kamu. Ia bertanya-tanya, kenapa sekarang aku semakin sering minta agar lampu dimatikan. Sebab yang aku bayangkan adalah wajah kamu, tubuh kamu.” (Saman, 2002:194).
Akan tetapi kepuasan seksual di mata Yasmin bukan hanya sebatas hubungan kelamin saja. Ia mempunyai pandangan sendiri tentang makna sebuah kepuasan seksual:
“Saman,
Orgasme dengan penis bukan sesuatu yang mutlak. Aku selalu orgasme jika membayangkan kamu. Aku orgasme karena keseluruhanmu.” (Saman, 2002:195).
Sama halnya dengan tokoh-tokoh perempuan lain dalam dwilogi novel ini, sikap Yasmin adalah perlawanan atas ketidakadilan. Laki-laki mempunyai kebebasan untuk memanjakan keliaran imajinasi seksualnya tanpa harus memusingkan efek moral di luar dirinya. Sedangkan perempuan terjebak dalam hegemoni budaya patriarki yang merepresi kebebasannya untuk menikmati nilai estetika seksualitas. Sebagai perempuan, Yasmin ingin kembali pada memori tentang naluri purbanya, dan baginya semua perempuan selama ini mengingkari insting alamiahnya karena dipasung oleh pengaruh di luar dirinya. Dengan Saman ia seolah menemukan kembali naluri itu dan bebas melampiaskannya:
“Bertahun-tahun aku hidup dengan fantasi itu, tanpa pernah mewujudkannya. Hingga hari aku bertemu kamu lagi. Kamu membangkitkan kembali khayal kanak-kanakku yang lama kukhianati. Tanpa kamu ketahui terlepaskanlah keperempuananku yang telah dipenjarakan hampir dua puluh tahun. Kini ia datang dengan memori purbanya. Seakan-akan ingatan primitif dari masa oral, ketika tubuhku belum diracuni oleh kekuatan luar yang mengagung-agungkan fallus dan memitoskan kesucian wanita. Ia datang dengan agresivitas yang murni, polos, inosen, yaitu dorongan untuk memakan, menghisap, mengconsume, mengexploit, memasukkan ke dalam dirinya benda-benda yang menarik hatinya. Juga kelamin laki-laki.” (Larung, 2002:161-162).
Saman yang hidup dalam kesendiriannya, dengan ketaatannya terhadap agama mampu dilumpuhkan Yasmin dengan naluri primitifnya. Di situlah letak kepuasan Yasmin terhadap Saman. Penaklukan atas keangkuhan soliternya. Hal tersebut juga yang menyebabkan Yasmin sangat tergila-gila kepada Saman dan bukan lelaki lain, termasuk suaminya sendiri. Dari sini bisa dilihat bahwa perselingkuhan yang dilakukan Yasmin selain disebabkan oleh alasan emosional dan seksual, juga merupakan wujud pemberontakan.
Berbeda dengan Laila dan Yasmin, perselingkuhan tokoh Cokorda Gita Magaresa tidak menjadi unsur penting di dalam dwilogi novel ini. Namun, Cok adalah tokoh perempuan yang paling membangkang dengan segala aturan yang ada di sekitarnya. Dialah sosok yang paling liar di antara teman-temannya, Laila, Yasmin, dan Shakuntala. Sejak remaja ia mempunyai kebiasaan gonta-ganti pacar. Meski, Shakuntala adalah orang pertama yang kehilangan keperawanan di antara mereka berempat, tetapi Cok yang lebih dulu melakukannya atas dasar keinginan dan kepuasan:
“Paling tidak, aku bisa menyombong bahwa akulah satu-satunya dari kami berempat yang pertama kali melakukan hubungan seks karena sadar dan suka. Shakuntala menghabisi keperawanannya lebih karena pemberontakan. Dia tidak menikmatinya. Laila masih suci-hama sampai sekarang. Dan Yasmin berbuat karena keterusan.” (Larung, 2002:86).
Karena keberanian Cok untuk membangkang dan melakukan seks bebas, ia dipindahkan dari sekolahnya di Jakarta ke Bali, dengan alasan pergaulan di Jakarta sudah rusak. Kedua orangtuanya menemukan kondom di dalam tasnya. Apa yang dialami Cok merupakan resiko sosial yang harus diterimanya ketika ia melanggar sistem nilai yang berlaku. Hal ini yang menyebabkan mengapa Laila begitu takut untuk melepaskan keperawanannya, keberanian pada dirinya nanti timbul ketika ia berada jauh dari Indonesia.
Cok melakukan selingkuh dengan seorang tentara, Brigjen. Rusdyan Wardhana. Sama halnya dengan pacar-pacarnya yang lain, dengan lelaki ini ia juga tak merasakan ketergantungan emosional. Di dalam setiap hubungan Cok selalu mengincar kepuasan-kepuasan lain di luar rasa cinta: seksual, kepentingan bisnis, dan lain-lain. Tetapi, sama halnya dengan perselingkuhan-perselingkuhan lain dalam dwilogi novel ini, tidak ada motivasi ekonomi yang mendasarinya. Cok adalah seorang pengusaha yang mengelola sebuah hotel miliknya sendiri.
Meski, perilaku seksual Laila dan Yasmin adalah pemberontakan, tapi hubungan mereka masih dilandasi dengan unsur perasaan yang mendalam, berbeda dengan Cok:
“Bagus, elu udah putus dari laki orang itu. Carilah bujangan, Cok. Jangan lakor. Bahaya.”
Masa?
“Lihat aja kasus Laila. Aku rasa dia dimain-mainkan saja oleh Sihar. Dijadikan selingan. Selingkuhan ringan.”
Lho, justru lakor itu aman, Min. Mereka nggak posesif karena punya keluarga. Bujangan cenderung mau menguasai kita. Dengan lakor, kita bisa putus dengan gampang.” (Larung, 2002:89).
Kutipan di atas bisa dilihat kalau Cok adalah perempuan yang tidak ingin terikat dengan laki-laki. Ia ingin bebas menikmati apapun tanpa ada sebuah ikatan. Ia pun tak akan menuntut lebih atau memaksakan setiap lelaki memberikan apa yang ia harapkan seperti yang dialami Laila. Cok adalah tipe perempuan yang mampu memerdekakan dirinya dari laki-laki.
Label: Esai
Dimensi Perselingkuhan Dalam Novel "Supernova" (Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh) Karya Dewi Lestari
 Secara umum perselingkuhan bisa diartikan sebagai penyelewengan yang terjadi pada suatu pasangan yang membangun sebuah hubungan, baik hubungan dalam ikatan pernikahan maupun yang tidak. Namun, pengertian secara khusus, yang paling sering dibahas dalam studi sosial budaya, selingkuh berarti, suami atau istri yang telah terikat dalam lembaga perkawinan, menjalin hubungan dengan laki-laki atau wanita lain dengan tanpa ikatan perkawinan. Unsur tanpa ikatan perkawinan harus ditegaskan mengingat di Indonesia poligami diperbolehkan.
Secara umum perselingkuhan bisa diartikan sebagai penyelewengan yang terjadi pada suatu pasangan yang membangun sebuah hubungan, baik hubungan dalam ikatan pernikahan maupun yang tidak. Namun, pengertian secara khusus, yang paling sering dibahas dalam studi sosial budaya, selingkuh berarti, suami atau istri yang telah terikat dalam lembaga perkawinan, menjalin hubungan dengan laki-laki atau wanita lain dengan tanpa ikatan perkawinan. Unsur tanpa ikatan perkawinan harus ditegaskan mengingat di Indonesia poligami diperbolehkan.
Perselingkuhan adalah problem sosial yang terjadi di mana saja sejak zaman dahulu kala, dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, miskin atau kaya, tua atau muda, dari pengusaha hingga pejabat. Problem ini berkaitan erat dengan masalah moral, agama, etika, institusi, dan lain-lain. Bahkan, banyak sekali konflik-konflik kekuasaan dalam sejarah dunia disebabkan oleh perselingkuhan. Salah satu contoh adalah perselingkuhan yang dilakukan mantan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, menjadi skandal besar yang menghebohkan dunia.
Di tengah masyarakat urban, perselingkuhan sudah menjadi gaya hidup. Kondisi ini tak terelakan mengingat seksualitas merupakan unsur alamiah yang terdapat pada manusia. Aktifitas pemuasan hasrat seks menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Setiap manusia berkecenderungan mencari objek pemuasan seks lain ketika ia tak lagi mendapat kepuasan dengan pasangan yang sebelumnya. Selain faktor dorongan biologis dan lingkungan sosial, perselingkuhan juga banyak disebabkan oleh faktor psikologis, pencarian akan rasa nyaman ketika pasangan terdahulu dirasa tidak cukup memberikan kebahagiaan. Akar dari masalah perselingkuhan memang kompleks.
Unsur perselingkuhan dalam novel ini ditampilkan pengarang lewat tokoh Ferre dan Rana. Kedua tokoh inilah yang oleh pengarang (Dewi Lestari) dan pencerita (Dhimas dan Ruben) disimbolkan sebagai Ksatria dan Puteri. Ferre dan Rana adalah dua sosok dengan latar belakang keluarga dan kehidupan yang berbeda. Ferre adalah seorang eksekutif muda tampan yang tengah menapaki puncak karirnya. Di usianya yang masih relatif muda ia telah memiliki segalanya, kekayaan, kesuksesan, kepopuleran, dan lain-lain. Karakternya sebagai sosok pekerja keras dan mandiri terbentuk sejak masih kecil. Ibunya meninggal ketika ia masih berumur 5 tahun. Sejak saat itu ia hidup bersama kakek dan neneknya yang juga meninggal ketika ia berumur 11 tahun. Kondisi tersebut membentuk dirinya menjadi sosok yang memiliki keperibadian kuat:
“Banyak yang mengira ia menjalani kehidupan jet set, bergelimang wanita cantik, dan pesta-pesta gila. Apa yang dibayangkan kebanyakan orang jauh berbeda dengan apa yang sesungguhnya ia jalani.
Ia selalu mendapatkan fasilitas nomor satu. Terbang dengan first class, mobil dinas setidaknya harga lima ratus jutaan, dan akomodasinya hampir selalu bintang lima. Namun ia melewati semuanya dalam keadaan berpikir, membuka-buka lembaran faks, menerima laporan ini-itu, telepon dari sana-sini yang tak mengizinkannya menikmati pemandangan jalan.” (2001:22).
Namun, di tengah puncak kesuksesan, Ferre belum juga mempunyai seorang pasangan hidup yang mendampinginya. Telah banyak wanita cantik mendekatinya tetapi tidak ada satu pun yang bisa memikat hatinya. Ia terlalu sibuk mengurusi pekerjaannya sebagai managing director di sebuah perusahaan multinasional. Suatu waktu seorang wartawan sebuah majalah perempuan menemuinya untuk diwawancara. Wartawan itu adalah seorang wanita yang telah menikah bernama Rana. Wawancara tersebut menjadi awal kisah cinta mereka. Saat berkenalan dengan Ferre, Rana sudah tiga tahun menikah. Bertolak belakang dengan Ferre, Rana dibesarkan oleh keluarga yang dipenuhi dengan aturan. Sejak kecil kehidupan Rana dikendalikan oleh orangtuanya.
Dr.Willard Harley (dalam Ni Luh Putu Suciptawati, Made Susilawati) mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan perselingkuhan adalah:
“Tidak bertemunya kebutuhan suami dan isteri dalam rumah tangga. Kebutuhan isteri meliputi kebutuhan akan kasih sayang (affection), percakapan (conversation), ketulusan dan keterbukaan (honesty and openness), komitmen finansial (financial commitment), dan komitmen keluarga (Family commitment). Sedangkan kebutuhan suami meliputi kebutuhan seksual (sexual fulfillment), kebersamaan dalam rekreasi (recreational companionship), memiliki pasangan yang menarik (an attractive spouse), dukungan dalam rumah tangga (domestic support), dan kekaguman (admiration)”. (http://ejournal.unud.ac.id).
Uraian di atas meski terlalu umum, memang cukup memadai untuk dijadikan acuan, karena cukup sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Satu faktor yang menjadi persamaan dan titik berat kebutuhan suami maupun isteri adalah faktor psikologis. Satu hal yang menarik, dan tentu saja bisa menimbulkan tarik menarik, yakni adanya dua unsur pembeda pada kebutuhan suami dan isteri. Kebutuhan seksual dan kebutuhan ekonomi. Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa perempuan lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi, sedangkan pria lebih memprioritaskan kebutuhan seksual. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa secara seksual perempuan memiliki kekuasaan lebih untuk mengendalikan laki-laki, sedangkan secara ekonomi laki-laki memiliki kekuasaan lebih untuk mengendalikan perempuan. Bila dilihat pada kasus-kasus yang terjadi di lapangan hal tersebut dapat dibenarkan. Laki-laki kaya sering memanfaatkan kekayaannya untuk memperoleh wanita cantik dan menarik supaya ia bisa memperoleh kepuasan sempurna secara seksual. Wanita pun sebaliknya, sering memanfaatkan kecantikannya untuk memikat hati pria-pria yang mapan secara ekonomi. Ditinjau dari sudut pandang sosiokultural pembagian kebutuhan tersebut sarat dengan politik budaya patriarkal, yang tidak memperhitungkan eksistensi perempuan.
Perselingkuhan dalam Supernova “Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh” memiliki dimensi tersendiri, karena pihak yang telah menikah adalah sosok perempuan. Bertolak belakang dengan kasus-kasus yang biasa terjadi di masyarakat, di mana kebanyakan hal tersebut dilakukan oleh pria yang telah menikah. Kasus tersebut identik dengan prinsip budaya patriarkal, laki-laki yang mapan meski telah berkeluarga bisa leluasa memperoleh pasangan selingkuh yang diinginkannya, dan perempuan mau saja dijadikan selingkuh asalkan laki-laki yang telah menikah tersebut memiliki kekayaan.
Pada umumnya perselingkuhan dapat dibagi menjadi dua tipe, Pertama, perselingkuhan dengan keterlibatan emosional yang rendah. Kedua, perselingkuhan dengan keterlibatan emosional yang tinggi dan mendalam (http://www.geocities.com/dien_99/data1/sebab.html). Sifat yang membedakan kedua tipe ini adalah perasaan yang dimiliki kedua pihak. Tipe pertama relatif hanya menitikberatkan pada kecocokan seksual. Sedangkan tipe kedua, selain kecocokan seksual, terdapat juga kecocokan kepribadian, dan kecocokan pemikiran atau ideologi. Frekuensi pertemuan bukanlah faktor penentu yang membedakan kedua tipe ini.
Perselingkuhan dalam novel ini termasuk pada tipe yang kedua. Rana, adalah pihak yang melakukan selingkuh. Sementara Ferre, pasangan selingkuhnya adalah lelaki yang tidak mempunyai pasangan. Pengarang dengan sengaja membuat perselingkuhan tersebut menjadi konflik yang unik. Faktor-faktor umum penyebab perselingkuhan seperti masalah ekonomi, kurang komunikasi, kurang kasih sayang, komitmen keluarga, tidak terdapat dalam novel ini. Suami Rana yaitu Arwin, adalah pria mapan dengan latarbelakang keluarga baik-baik. Arwin dengan tulus selalu memperhatikan kebutuhan Rana dan keharmonisan hubungan mereka seperti terdapat dalam kutipan berikut: “Arwin memandangi istrinya yang sedang menunduk menghadapi piring, menunggu saat-saat tepat untuk mulai berbicara.
“Arwin memandangi istrinya yang sedang menunduk menghadapi piring, menunggu saat-saat tepat untuk mulai berbicara.
“Rana...,” panggilnya lembut.
“Ya, Mas?”
“Kamu kok jadi pendiam sih akhir-akhir ini? Ada masalah yang bisa aku bantu?”
Rana menunduk lagi. Ya, Mas. Aku jatuh cinta dengan pria lain. Bisakah kita kembali ke masa lalu dan tidak perlu menikah?
“Kalau Mas ada salah sama kamu, bilang saja. Jangan dipendam-pendam. Komunikasi di antara kita harus dijaga tetap lancar,” dengan lebih lembut Arwin berkata.
“Mas Arwin nggak ada salah apa-apa, kok?.” Itulah satu-satunya kesalahanmu, Mas.
“Kamu sehat-sehat, kan? Kapan terakhir kali check-up ke dokter?” (2001:40).
Kalimat-kalimat yang bergaris miring dalam kutipan di atas adalah ungkapan isi hati Rana. Lewat kutipan tersebut dapat dilihat bahwa Arwin sangat sayang dan perhatian pada istrinya. Jadi, bisa dikatakan bahwa apa yang dibutuhkan Rana pada seorang lelaki, semuanya ada dalam diri Arwin, kecuali satu, cinta. Bagi masyarakat modern dewasa ini alasan Rana mungkin terlalu naif. Tetapi, itulah sisi yang coba diangkat pengarang, di tengah arus budaya kapitalis yang semakin dahsyat dewasa ini, di mana segala sesuatu diukur dengan materi Dewi Lestari menyisipkan sesuatu yang menjadi nilai hakiki manusia yakni cinta. Meski, demi merebut cinta tersebut banyak hal yang harus dikorbankan, perkawinan, perasaan suami, orangtua, dan lain-lain.
Namun, seperti dijelaskan sebelumnya, keputusan Rana menikahi Arwin memang lebih banyak dipengaruhi orangtuanya. Karena sejak kecil gerak-geriknya dikendalikan penuh oleh orangtua. Ia tak mempunyai kebebasan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Sebelumnya ia merasa nyaman-nyaman saja hidup di bawah aturan seperti itu. Tetapi, setelah bertemu dengan Ferre ia baru menyadari bahwa ia telah dikungkung begitu jauh, dan ia pun menemukan cintanya.
Dapat dilihat bahwa kisah cinta Rana dan Ferre mengandung beragam konflik. Konflik terbesar tentu dialami tokoh Rana, ia harus bergelut dengan pertentangan batin, moral, agama, institusi, dan lain-lain, seperti yang tampak dalam kutipan berikut ini:
“Ikatan saya banyak. Bukan hanya pernikahan dua orang, tapi saya juga menikah dengan keluarganya. Dengan segenap lapisan sosialnya. Saya tidak seperti kamu yang punya banyak kebebasan. Kamu tidak bisa membandingkan...”
Re memutar tubuh Rana, menatapnya lurus-lurus. “Saya tidak membandingkan, karena saya tahu persis pembandingan tidak akan membawa kita ke mana-mana. Tapi saya bisa melihat kamu memilikinya. Kekuatan untuk mendobrak. Membebaskan diri kamu sendiri.”
“Mendobrak apa? Moralitas? Norma sosial? Kita hidup di dalamnya, Re. Saya cuma ingin mencoba realistis...” (2001:85).
Perselingkuhan bagaimanapun di dalam masyarakat Indonesia memang dianggap haram, amoral, dan melawan hukum. Tetapi, di satu sisi rasa cinta tulus yang mereka punyai adalah sesuatu yang hakiki, menyangkut kebahagiaan mereka sebagai manusia, seperti dalam lanjutan kutipan tadi:
“Tidakkah kamu menyakiti dirimu sendiri dengan menempatkannya demikian? Apa yang jahat di sini, Rana? Jahatkah saya mencintai kamu mati-matian? Begitu amoralkah semua perasaan ini?”
Rana mendapatkan dirinya dalam dilema yang sama, lagi dan lagi. Ia lelah.” (2001:86).
Di dalam hal ini pengarang mencoba menjelaskan bahwa sistem yang terdapat dalam masyarakat, baik sistem hukum, agama, sosial, kadang menjadi penghambat bagi setiap orang dalam menempuh sebuah nilai yang substansial.
Satu hal yang di luar dugaan, ketika mengetahui istrinya menjalin hubungan gelap dengan lelaki lain, tidak ada setitik pun amarah meluap dalam diri Arwin. Karena begitu besar cintanya kepada Rana, Arwin pasrah asalkan istrinya bisa merasakan kebahagiaan. Suasana hati Arwin tampak dalam kutipan berikut ini:
“Tak ada kebencian yang bisa ia keruk dari dalam hatinya untuk Rana. Tidak juga untuk pria itu. Yang ada hanyalah kebencian pada dirinya sendiri.
Ya, aku memang tidak pernah pantas memilikinya. Bertahun-tahun aku tahu itu, tapi aku diam saja. Egois. Tidak pernah satu detik pun aku mampu membuat Rana bersinar bahagia seperti itu. Aku pikir aku telah seluruhnya mencintai, padahal aku hanyalah batu penghalang bagi kebahagiaannya. Maafkan aku Rana. Hanya sebeginilah kemampuanku. Andaikan aku bisa berbuat lebih...”(2001:113).
Ketabahan dan kerelaan tokoh Arwin memiliki nilai filosofis yang mendalam, bahwa kadang perselingkuhan ternyata tidak butuh sebab, tidak butuh alasan, terjadi begitu saja ketika hal tersebut sudah menyangkut masalah cinta dan kebahagiaan individu manusia. Ketabahan seperti itu sudah sangat jarang, atau bahkan tidak mungkin sama sekali ditemukan dalam masyarakat sekarang ini. Arwin pun merelakan istrinya menentukan pilihannya sendiri. Ia tak ingin menghalang-halangi kebahagiaan istrinya. Baginya cinta seharusnya membebaskan:
“Lama aku berusaha menyangkal kenyataan ini, tapi sekarang tidak lagi. Kamu memang pantas mendapatkan yang lebih. Maafkan aku tidak pernah menjadi sosok yang kamu inginkan. Tidak menjadikan pernikahan ini seperti apa yang kau impikan. Tapi aku teramat mencintaimu, istriku...atau bukan. Kamu tetap Rana Yang kupuja. Dan aku yakin tidak akan ada yang melebihi perasaan ini. Andaikan saja kamu tahu.” (2001:161).
Ketabahan ini pula yang menimbulkan hikmah besar pada Arwin, yang membuat Rana melihat Arwin sebagai sosok yang baru, yang mengerti arti cinta sesungguhnya. Rana begitu tersentuh dengan kerelaan suaminya:
“Ada satu makna yang secara aneh terungkap: cinta yang membebaskan. Ternyata Arwin yang punya itu. Bukan dirinya, bahkan bukan pula kekasihnya.
Giliran Arwin yang terenyak ketika istrinya malah menghambur jatuh, mendekapnya erat-erat. Rasanya itu bukanlah pelukan perpisahan, melainkan sebaliknya, pelukan seseorang yang kembali.” (2001:162).
Kisah cinta yang dialami Rana dengan Ferre seolah terkesan mencapai titik antiklimaks. Namun, itulah klimaks yang sesungguhnya ketika Rana mulai belajar mengerti makna cinta yang sebenarnya di saat ia mengkhinati suaminya. Ia pun akhirnya kembali ke dalam pelukan sang suami yang mencintainya tanpa menuntut Rana membalas cintanya. Ini justru terjadi ketika Rana sudah mendapatkan kebebasan untuk bahagia bersama Ferre. Secara implisit pengarang coba menyampaikan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini, semuanya serba relatif, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan, termasuk masalah cinta.
Label: Esai
Sosok Pelacur Dalam Novel "Supernova" (Ksatria, Puteri, Dan Bintang Jatuh) Karya Dewi Lestari (Sebuah Perlawanan Terhadap Budaya Patriarkhi)
 Ditinjau lewat aspek penokohan, maka akan ditemukan bahwa Diva adalah tokoh utama dalam novel ini. Sosok bintang jatuh yang digambarkan pengarang (Dewi Lestari) maupun pencerita (Dhimas dan Ruben) tak lain adalah perempuan cantik yang sering menjajahkan tubuhnya kepada banyak lelaki ini. Menurut kacamata masyarakat umum, apalagi dalam konteks budaya Indonesia, perempuan yang menjajahkan tubuhnya pada lebih dari satu lelaki tanpa ada ikatan resmi dan menerima imbalan berupa uang disebut pelacur.
Ditinjau lewat aspek penokohan, maka akan ditemukan bahwa Diva adalah tokoh utama dalam novel ini. Sosok bintang jatuh yang digambarkan pengarang (Dewi Lestari) maupun pencerita (Dhimas dan Ruben) tak lain adalah perempuan cantik yang sering menjajahkan tubuhnya kepada banyak lelaki ini. Menurut kacamata masyarakat umum, apalagi dalam konteks budaya Indonesia, perempuan yang menjajahkan tubuhnya pada lebih dari satu lelaki tanpa ada ikatan resmi dan menerima imbalan berupa uang disebut pelacur.
Encyclopaedia Britannica (dalam Dam Truong, 1992:15) mendefinisikan pelacuran sebagai:
“praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran dikarakterisasikan oleh tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidak acuhan emosional”
Definisi tersebut khususnya tiga unsur yang dipaparkan di atas sangat sesuai dengan karatkteristik yang terdapat pada tokoh Diva. Meskipun definisi ini mempunyai kelemahan karena dua dari tiga unsur tadi tidak bisa diterapkan di semua situasi. Kita tidak bisa mengatakan setiap aksi pelacuran selalu dilandasi ketidak acuhan emosional ataupun pembayaran. Bagaimana dengan kasus ketika seorang perempuan melakukan hubungan intim dengan banyak lelaki (tanpa ikatan resmi), namun ia sendiri melibatkan unsur emosional dan menerima bayaran?. Jelas bahwa dalam hal ini kriteria ekonomi semata juga memang tidaklah memadai. Kita juga tidak bisa mengatakan bila hubungan intim dalam sebuah ikatan resmi sama sekali bebas dari tindakan pembayaran. Banyaknya tarik menarik mengenai konsepsi pelacuran oleh banyak ilmuwan dikarenakan setiap konsep tidak selalu bisa diterapkan pada semua kebudayaan masyarakat. Semua bergantung dari etos budaya yang terdapat di pusat konstruksi sosial norma-norma seksual (Dam Truong, 1992:13).
Secara lebih luas istilah pelacur kadang ditempelkan kepada seseorang yang menjual keahliannya untuk sesuatu yang tak berharga. Contohnya, seorang seniman yang mempunyai potensi besar di bidangnya, namun lebih condong membuat karya-karya yang sifatnya komersil. Ia dianggap melacurkan diri karena mengorbankan idealismenya. Di dalam etika kristen juga terdapat makna pelacuran yang lebih luas, yakni tindakan penyembahan terhadap dewa-dewa lain selain Allah. Hal ini dijelaskan dalam kitabYehezkiel pasal 23 dan kitab Hosea (1:2-11).
Dijelaskan Ihsan (dalam Wakhudin) para antropolog mengatakan, adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah terjadi sejak zaman primitif, menyebabkan pelacuran menjadi realitas yang tak mungkin terelakkan. (http://akhmadsudrajat.wordpress.com) Tugas perempuan diarahkan untuk melayani kebutuhan seks lelaki. Sedangkan kaum feminis menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pelacuran karena kuatnya sistem dan budaya patriarkhi. Sementara kaum marxis menganggap pelacuran merupakan resiko dari sistem kapitalisme.
Pada perkembangannya kedudukan pelacur mengalami naik turun. Menurut sejarah, bentuk pelacuran tertua ditemukan di negara-negara kuno seperti India dan Babilonia Kuno (Dam truong, 1992:20). Waktu itu tindakan pelacuran identik dengan berbagai ritus keagamaan. Sebagai contoh di Babilonia Kuno, perempuan-perempuan yang berafiliasi dengan monumen yang dianggap keramat, seperti candi, melakukan hubungan seks (melacurkan diri) dengan para pengunjung tempat tersebut. Hal ini sebagai wujud pemujaan atas kesuburan dan kekuasaan seksual para dewi. Untuk hal tersebut diberikan sumbangan untuk candi. Contoh lain ditambahkan Ihsan (dalam Wakhudin), adalah perempuan-perempuan yang menjajahkan dirinya diberbagai tempat, dan penghasilannya diberikan kepada pendeta untuk kepentingan kuil. (http://akhmadsudrajat.wordpress.com). Mereka dikenal dengan istilah “pelacur kuil” (temple prostitutes).
Pelacuran zaman tersebut identik dengan pengabdian untuk kepentingan keagamaan. Jadi, kedudukan sosialnya dianggap terhormat. Contoh lain yang tidak ada hubungannya dengan religi terdapat di negara-negara Asia Timur. Di Jepang terkenal dengan Geisha, perempuan penjajah seks yang dibekali dengan berbagai kemampuan seni, seperti memainkan bermacam alat musik, menari, berpuisi, dan lain-lain. Geisha berasal dari kata Gei yang artinya seni, dan Sha yang berarti pribadi. Budaya Jepang menganggap Geisha adalah artis. Perempuan-perempuan yang menjadi Geisha memiliki latarbelakang kelas yang beragam. Namun, pengaruh sosial dan hak istimewa yang mereka dapatkan tergantung juga dengan pria siapa mereka melakukan hubungan. Dari contoh tadi kita bisa melihat, demi kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan keagamaan dan penguasa, pelacuran tidak dicerca melainkan menjadi sesuatu yang dihargai.
Pelacuran di mata masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang buruk, haram, hina, dan lain-lain. Wanita yang menjadi pekerja seks dianggap sebagai sampah masyarakat, perusak moral, penyebar berbagai macam penyakit. Baik agama maupun hukum melarang praktek prostitusi. Meski, di daerah-daerah tertentu seperti Surabaya terdapat lokalisasi PSK yang legal. Augustinus dari Hippo 354-430), seorang bapak gereja pernah mengatakan bahwa, pelacuran itu ibarat "selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya."(http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran). Sesuatu yang ironi memang, ternyata di tengah stigma yang disandangnya, pelacur juga dibutuhkan, dan sebagai solusi dari sebuah problem sosial untuk mengurangi kasus-kasus pemerkosaan di tengah masyarakat. Anggota masyarakat yang menggunakan jasa pekerja seks sama sekali tak menanggung stigma seperti yang dikenakan pada pelacur.
Rowbothan (dalam Dam Truong, 1992:17) berpendapat bahwa istilah pelacuran merupakan perwujudan dari hegemoni kultural. Pemisahan antara istri (perempuan terhormat, gundik (perempuan piaraan), pelacur (perempuan sundal) tak lain demi kepentingan dominasi pria. Karakter Diva, berkaitan dengan pendapat tadi bisa dikatakan sebagai media pengarang untuk melawan hegemoni kultural tersebut. Diva berprofesi sebagai peragawati kelas atas. Imbalan yang dimintanya setiap kali naik panggung jumlahnya tidak sembarangan. Di samping itu, ia juga selektif dalam memilih acara. Bahkan, hanya majalah-majalah bona fide saja yang bisa memamerkan foto-fotonya. Standar tinggi tersebut sepadan dengan profesionalitas dan disiplin yang dijalankannya. Hingga kesan yang akan timbul selanjutnya adalah Diva tipe perempuan pekerja keras dan konsisten dengan pekerjaannya. Tokoh Diva merupakan refleksi pengarang akan kenyataan yang sudah menjadi rahasia umum dalam kehidupan kota metropolitan, banyaknya model yang juga berprofesi sebagai wanita penghibur. Pelacuran terselubung kelas tinggi yang hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, yaitu mereka yang memiliki kemampuan ekonomi mapan. Satu hal yang menarik, sebagian dari para pelacur ini memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Jadi, menganggap masalah ekonomi sebagai satu-satunya faktor yang melatarbelakangi tindakan pelacuran adalah keliru. Banyak faktor lain yang bisa dkatakan menjadi penyebab, seperti lingkungan pergaulan, gaya hidup yang konsumtif (membuat setiap orang ingin memperoleh uang dengan cepat dan mudah), lingkungan keluarga, dan lain-lain.
Diva memiliki hubungan intim dengan beberapa lelaki, dan ia juga menuntut upah untuk hubungan tersebut. Dari seorang pengusaha kaya bernama Dahlan hingga seorang pemuda kaya beristeri seperti Nanda. Tindakan “menjual diri” tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak terhormat. Ia mempunyai sebuah pembenaran yang ia yakini sebagai dasar pemikiran atas tindakannya itu. Kemampuan berpikir dan luasnya wawasan yang dimiliki Diva memang sangat kontradiktif dengan profesi sampingan yang dijalankannya. Bagaimana mungkin perempuan cerdas dan berkepribadian kuat seperti dirinya rela menjual tubuhnya untuk dinikmati banyak lelaki?. Tapi ia pun memiliki pembenaran atas semua itu. Gambaran ideologi yang mendasari pilihan hidupnya terdapat dalam kutipan berikut ini:
“Wanita itu tersenyum mencemooh. “Justru karena saya lebih pintar dari kamu dan CEO kamu, makanya saya tidak mau bekerja seperti kalian. Apa bedanya profesi kita? Sudah saya bilang, kita sama-sama berdagang. Komoditasnya saja beda. Apa yang kamu perdagangkan buat saya tidak seharusnya dijual. Pikiran saya harus dibuat merdeka. Toh, berdagang pun saya tidak sembarang...”(2001: 57).
Dari perkataan tokoh tersebut bisa dilihat konsep ideologi yang dipegang olehnya. Bagi Diva, apa yang diperdagangkan oleh para kapitalis adalah sesuatu yang seharusnya tidak dijual, karena sesuai dengan prinsip marxisme, semua itu seharusnya adalah kepemilikan bersama. Sementara ia sendiri menjual tubuhnya, kecantikannya, menurutnya adalah sesuatu yang wajar. Karena keindahan tubuh dan kecantikannya adalah miliknya sendiri. Ia memiliki kemerdekaan untuk menjualnya kepada siapapun.
Diva adalah tipe perempuan yang nyaris sempurna. Memiliki kecantikan, keindahan tubuh, karir yang sukes, kecukupan ekonomi, kecerdasan, dan menjunjung tinggi kebebasan perempuan. Selain itu, ia juga perfeksionis dalam segala hal, baik dalam hal pekerjaan, maupun pandangan tentang hidup. Namun, ia pun sadar, ia hidup pada masa ketika uang memiliki peranan utama bagi setiap orang untuk dapat mempertahankan diri. Semua hal yang ia lakukan baginya adalah resiko hidup di zaman kapitalis, termasuk “memperdagangkan” tubuhnya sendiri:
“Ia tahu, pekerjaannya membutuhkan fisik yang selalu fit, penampilan yang prima. Tapi semua itu dilakukannya semata-mata karena ia merasa berkewajiban mengurus jasad – kendaraannya untuk menghadapi hidup. Dan kendaraan ini bukan kendaraan rombeng. Ia tidak akan pernah memperlakukannya demikian. Setiap tubuh adalah perangkat yang luar biasa menakjubkan.” (2001:92).
Di zaman kapitalis manusia hampir tidak lagi mempedulikan masalah ketulusan cinta dan hati nurani. Segala sesuatu diukur dengan uang. Orang kaya semakin kaya, dan orang miskin makin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan. Bila ingin tetap bertahan hidup semua orang harus rela membiarkan dirinya terseret dalam arus tersebut. Tapi, Diva beranggapan bahwa bagaimana pun cinta tak akan bisa diperjualbelikan. Nanda, lelaki beristri yang berkencan dengannya, sangat mengagumi kepribadian Diva. Hingga ia pun mengatakan, ia lebih memilih uangnya dibayar untuk merasakan kasih sayang Diva, daripada bersetubuh dengannya:
“Ketulusan bukan ketulusan lagi kalau kita mulai memperjualbelikannya. Saya memang punya dagangan, sama seperti kamu. Kita sama-sama harus begitu untuk bertahan di dunianya tukang dagang. Tapi jangan cemari satu-satunya jalan pulangmu untuk keluar dari semua sampah ini, kembali ke diri kamu sebenarnya. Sorot mata yang hidup tadi, digerakkan kejujuran yang berontak dari dalam sana. Terkutuklah Diva si pelacur begitu ia mulai memunguti uang di atasnya. Ya, terkutuklah dia.” (2001:66).
Karakteristik tokoh yang paradoksal merupakan ciri khusus novel ini. Eksplorasi jenis tokoh seperti ini tampaknya dilakukan dengan sadar oleh pengarang, sebagai perlawanan terhadap norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam kacamata masyarakat, tindakan pelacuran pada umumnya dilatar belakangi pergaulan yang tidak baik atau kondisi ekonomi yang di bawah standar. Anggapan ini jelas sangat bertolak belakang dengan karakteristik seorang Diva. Sebagai seorang peragawati papan atas, kondisi ekonomi yang menopangnya cukup memadai. Di dalam cerita juga tidak digambarkan jika dirinya memiliki pergaulan buruk, yang menyeretnya pada kebiasaan seperti itu. Diva bahkan ditampilkan pengarang sebagai sosok perempuan cerdas dan memiliki wawasan luas, juga peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Stigma yang menempel pada pelacur coba dijungkirbalikan pengarang lewat tokoh Diva, namun di sisi lain, sang pengarang pun tidak bermaksud untuk mengubahnya menjadi positif, yang ditonjolkan di sini adalah sebuah sikap, pemikiran yang dimiliki sang tokoh.
Label: Esai
Homoseksualitas Dalam Novel “Supernova” (Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh) Karya Dewi Lestari (Suatu Tinjauan Sosial, Budaya, Moral)
 Insting seksual lazimnya terjadi antara pria kepada wanita maupun sebaliknya. Namun, banyak juga didapati keinginan seksual yang menyimpang dari biasanya. Pria menyukai pria dan wanita menyukai wanita. Secara umum mereka dikategorikan sebagai pasangan homoseksual. Wikipedia bahasa Indonesia menjelaskan bahwa:
Insting seksual lazimnya terjadi antara pria kepada wanita maupun sebaliknya. Namun, banyak juga didapati keinginan seksual yang menyimpang dari biasanya. Pria menyukai pria dan wanita menyukai wanita. Secara umum mereka dikategorikan sebagai pasangan homoseksual. Wikipedia bahasa Indonesia menjelaskan bahwa:
“Homoseksualitas mengacu pada interaksi seksual dan/atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama. Pada penggunaan mutakhir, kata sifat homoseks digunakan untuk hubungan intim dan/atau hubungan sexual di antara orang-orang berjenis kelamin yang sama, yang bisa jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau lesbian. Homoseksualitas, sebagai suatu pengenal, pada umumnya dibandingkan dengan heteroseksualitas dan biseksualitas. Istilah gay adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseks. Sedangkan Lesbian adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada wanita homoseks” (http://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas).
Sigmund Freud mengkategorikan mereka yang memiliki insting seksual ke sesama jenis sebagai manusia berperilaku seksual terbalik, atau disebut juga dengan Invert (2003:2-3). Perilaku invert itu sendiri terbagi dalam beberapa jenis, sesuai sifat atau kecenderungan yang dimiliki. Jenis yang pertama adalah mereka yang memiliki kecenderungan terbalik dalam dua arah, atau psychosexually hermaphroditic. Kelompok ini memiliki orientasi seksual secara umum, baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis, sehingga karakter invert mereka tidak menampakkan kekhususannya. Kelompok ini dalam masyarakat kota juga kita kenal dengan sebutan biseksual, misalnya seorang lelaki yang bisa berhubungan seks dengan lelaki ataupun perempuan. Jenis yang kedua adalah mereka yang hanya sesekali saja menampakkan perilaku invertnya, atau occasionally inverted. Kelompok ini menunjukkan karakter invertnya hanya dalam situasi tertentu saja. Misalnya, ketika kebutuhan objek seksual lawan jenis tidak terpenuhi, sehingga mereka memilih sesama jenis sebagai objek pemuasan seksual mereka. Kasus seperti ini banyak terjadi di dalam lingkungan penjara. Banyak tahanan yang menjadi korban sodomi dari tahanan lain dikarenakan tidak adanya pelampiasan seksual kepada lawan jenis. Contoh yang sama juga terjadi di masyarakat metropolitan, demi tujuan-tujuan tertentu, seperti popularitas, uang, dan lain-lain, banyak lelaki yang mempunyai orientasi seksual normal, melakukan hubungan intim dengan seorang homoseks. Di dalam novel Supernova (Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh), Dhimas dan Ruben adalah pasangan Gay. Kedua tokoh ini termasuk dalam kategori ketiga yaitu, absolutely inverted, Freud menjelaskan bahwa:
“Objek seksual mereka harus selalu berasal dari jenis kelamin yang sama. Bahkan bagi kelompok ini, lawan jenis tidak akan pernah mampu menjadi objek kerinduan seksual; lawan jenis hanya akan diacuhkan, bahkan mungkin menumbuhkan rasa jijik. Kemunculan rasa jijik ini, bagi kaum pria, membuat mereka tidak mampu melakukan aktivitas seksual normal atau kehilangan segala kenikmatan dalam melakukannya” (2003:3).
Sejarah homoseksual dunia sudah sangat tua, dahulu kita kenal dengan peristiwa Sodom dan Gomorah yang terdapat dalam alkitab perjanjian lama. Homoseksualitas merupakan praktek universal, dilakukan di mana pun, dan dalam kebudayaan apapun. Bahkan, empat belas dari lima belas kaisar Roma yang pertama adalah gay. Menurut Dede Oetomo, homofilia atau homoseksualitas terdapat di mana saja dalam kehidupan manusia karena secara biologis-psikologis manusia dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan tindakan seks yang jauh lebih banyak macamnya daripada hanya senggama penis dengan vagina. (http://itha.wordpress.com/2007/08/27/menyikapi-masalah-homoseksualitas).
Penggunaan pertama kata homoseksual yang tercatat dalam sejarah adalah pada tahun 1869 oleh Karl-Maria Kertbeny, dan kemudian dipopulerkan penggunaannya oleh Richard Freiherr von Krafft-Ebing pada bukunya Psychopathia Sexualis (-http://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas). Di dalam beberapa masyarakat, peran homoseksual bahkan dilembagakan. Seperti pada Suku Koniag, yang mensosialisasikan beberapa anak laki-laki sejak bayi untuk mengisi peran
wanita. Di kalangan Suku Siwan di Afrika, semua laki-laki dan anak laki-laki
diharapkan melakukan senggama anal dan ganjil bila tidak melakukannya (http://digilib.petra.ac.id/ads-cgi/viewer.pl/jiunkpe/s1/ikom/2006). Suku Dayak Ngaju mengharuskan tetua yang dipilih adalah seseorang yang berhubungan seks dengan sesama jenis kelamin. Pelembagaan Homoseksual yang kebanyakan terjadi pada masyarakat yang memiliki sedikit surplus sosial, identik dengan masalah produksi kebutuhan material masyarakat itu sendiri. Jumlah penduduk berlebihan pada kehidupan masyarakat yang masih memiliki metode kerja manual dan teknologi sederhana, akan menyebabkan kebutuhan material dengan jumlah penduduk mengalami ketimpangan. Hal ini menyebabkan munculnya mitos-mitos seputar masalah biologis yang melembagakan hubungan sesama jenis, dan melemahkan peranan hubungan heteroseksual, demi mengendalikan populasi penduduk.
Salah satu contoh suku bangsa Etoro, sebuah kelompok masyarakat yang bermukim di daerah Trans-fly Papua New Guinea, dengan jumlah penduduk sekitar 400 jiwa. Pandangan dan perilaku seksual orang Etoro berhubungan dengan kepercayaan-kepercayaan di sekitar siklus kelahiran, pertumbuhan fisik, kedewasaan, ketuaan, dan kematian (-http://www.e-samarinda.com/forum/index.). Kebudayaan Etoro menganggap perempuan adalah mahluk berbahaya dan tercemar, sehingga aktifitas persenggamaan bagi mereka adalah perilaku kotor. Hubungan seks heteroseksual hanya dilakukan untuk keperluan reproduksi, itu pun diperbolehkan hanya 100 hari dalam setahun. Di luar itu, persenggamaan dengan lawan jenis dianggap tabu. Mereka juga percaya anak-anak muda pria belum bisa menghasilkan spermanya sendiri, untuk itu membutuhkan sperma secara oral dari laki-laki yang lebih tua. Orang Etoro yakin sperma lelaki bisa memberi kekuatan hidup. Walaupun persenggamaan tidak disukai, aktifitas homoseksual diperbolehkan bahkan dianggap penting. Jadi, kehidupan homoseksual masyarakat seperti itu tidak didasari oleh dorongan patologi biologis, faktor genetika, atau hubungan emosional, tetapi lebih didasari oleh faktor kebudayaan, tradisi, yang memiliki kaitan erat dengan kondisi produksi material. Sejak peristiwa Stonewall tahun 1969 yang dikenal sebagai peristiwa pembangkangan kaum homoseksual dalam memperjuangkan hak-haknya, yang juga bersamaan dengan gelombang kedua gerakan perempuan, homoseksual menjadi gerakan yang nyata, tidak lagi sembunyi-sembunyi, dan secara serius mulai menjadi bahan kajian studi sosial budaya. Di beberapa Negara tertentu seperti Belanda dan Kanada, pasangan homoseksual sudah bisa meresmikan ikatan hubungan mereka dalam pernikahan. Di Indonesia sendiri, homoseksual dalam beberapa tahun terakhir mulai berani dieksplorasi lewat media-media komunikasi massa, sebagai masalah sosial yang mau diterima atau tidak memang ada di sekitar kita. Contohnya lewat film dan karya sastra. Selain Supernova “Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh”, novel-novel Indonesia lainnya yang mengangkat homoseksualitas antara lain, “Relung-Relung Gelap Hati Sisi” karya Mira W, dan “Manusia-Manusia” karya Bagus Utama. Sejak zaman Balai Pustaka dan Pujangga Baru, para pengarang masih menganggap tema ini adalah tabu untuk ditampilkan dalam karya sastra. Sampai sekarang pun, meski tidak setabu dahulu, sastrawan yang mengangkat masalah tersebut masih tergolong minim.
Sejak peristiwa Stonewall tahun 1969 yang dikenal sebagai peristiwa pembangkangan kaum homoseksual dalam memperjuangkan hak-haknya, yang juga bersamaan dengan gelombang kedua gerakan perempuan, homoseksual menjadi gerakan yang nyata, tidak lagi sembunyi-sembunyi, dan secara serius mulai menjadi bahan kajian studi sosial budaya. Di beberapa Negara tertentu seperti Belanda dan Kanada, pasangan homoseksual sudah bisa meresmikan ikatan hubungan mereka dalam pernikahan. Di Indonesia sendiri, homoseksual dalam beberapa tahun terakhir mulai berani dieksplorasi lewat media-media komunikasi massa, sebagai masalah sosial yang mau diterima atau tidak memang ada di sekitar kita. Contohnya lewat film dan karya sastra. Selain Supernova “Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh”, novel-novel Indonesia lainnya yang mengangkat homoseksualitas antara lain, “Relung-Relung Gelap Hati Sisi” karya Mira W, dan “Manusia-Manusia” karya Bagus Utama. Sejak zaman Balai Pustaka dan Pujangga Baru, para pengarang masih menganggap tema ini adalah tabu untuk ditampilkan dalam karya sastra. Sampai sekarang pun, meski tidak setabu dahulu, sastrawan yang mengangkat masalah tersebut masih tergolong minim.
Secara umum harus diakui bila fenomena gay memang masih dianggap menyimpang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya angka resmi mereka yang menyatakan diri sebagai gay. Agama-agama yang ada di Indonesia sendiri memang menentang keberadaan homoseksual. Masyarakat kita seolah masih terjebak pada dualisme antara ingin menolak fenomena kaum tersebut, dan harus menerima kenyataan bahwa mereka ada di tengah-tengah kita.
Di kota metropolitan seperti Jakarta, kaum pencinta sesama jenis sudah cukup bisa diterima dan bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh di mata sebagian besar masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya media audio visual yang merupakan sumber informasi paling besar bagi masyarakat, sudah sering mengangkatnya sebagai masalah sosial. Tetapi, di sisi lain eksistensi mereka memang seringkali ditanggapi dengan respon negatif. Di dalam kehidupan sosial sehari-hari kaum homoseksual sering kita jumpai memiliki profesi yang dianggap remeh masyarakat. Pekerja seks, atau keahlian-keahlian lain yang berhubungan dengan penampilan luar. Masyarakat beranggapan seorang homoseks tidak bisa melakukan apapun, selain hanya bisa mengumbar dan memuaskan dorongan seksual mereka. Tidak perlu heran bila keberadaan kaum homoseksual sering ditertawakan. Bahkan, belakangan dijumpai seorang homoseksual melakukan pembunuhan berantai dengan memutilasi korbannya. Contoh-contoh tersebut, mengakibatkan penempelan sebuah stigma sulit untuk dihindari. Kaum homoseksual dikutuk, dijauhi, bahkan ditakuti. Masyarakat kita seolah mengalami kebencian besar terhadap mereka.
Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari, (http://muhsinlabib. Wordpress.com/2007/07/19/homoseksualitas-kawin-sejenis-atau-ganti-kelamin), perilaku homoseksual tidak hanya diakibatkan oleh faktor natural semata seperti kelebihan hormon, namun juga merupakan problema psikologis (kejiwaan), sebagai akibat dari interaksi dan komunikasi bebas serta hilangnya pembatas moral antar lawan jenis.
Ia menambahkan, ada dua faktor utama yang menjadi penyebab homoseksualitas. Pertama adalah pengalaman traumatik di masa lalu, misalnya seseorang pernah menjadi korban sodomi, sehingga ia ingin membalas apa yang telah dialami kepada orang lain. Itu sebabnya homoseksualitas kerap dianggap sebagai penyakit menular. Kedua, pengaruh budaya dan komunikasi yang bebas. Fenomena seperti ini sering terjadi di kalangan selebritis. Misalnya, para artis, pada saat akan melakukan pertunjukan, shooting film ataupun show lainnya, harus berganti busana dalam waktu yang singkat karena kejar waktu, meski harus ‘telanjang’ di hadapan lawan jenisnya. Intensitas kontak indra yang sering, membuat mereka menjadi bosan dengan pemandangan ini dan mencari ’sensasi’ baru dengan melepaskan kecenderungan biologisnya kepada sesama jenis yang mengalami hal serupa. Tetapi contoh tersebut tidak sepenuhnya benar, karena seorang lelaki yang telah menikah bisa dibilang setiap hari melihat istrinya tanpa pakaian, namun ia tidak mengalami kejenuhan apalagi sampai berubah orientasi seksualnya. Pengaruh lingkungan keluarga juga bisa menjadi penyebab, misalnya seorang anak laki-laki dididik dan diperlakukan sebagai perempuan oleh orangtua dikarenakan keinginan untuk memperoleh anak perempuan yang tidak kesampaian. Novel ini mengangkat sisi minor, atau sisi yang jarang dilihat dari kaum homoseksual. Lewat teks, pengarang ingin menjungkirbalikkan anggapan-anggapan negatif masyarakat yang telah menjadi stereotip tadi. Kaum homoseksual tidak selamanya seperti yang mereka pikirkan, tetapi banyak juga dari mereka yang menjadi pemikir dan memiliki visi yang hebat di bidangnya. Bahkan tokoh-tokoh besar dunia seperti Plato, Foucault, Alexander The Great, dan Leonardo Da Vinci adalah seorang gay. Di sini pengarang mencoba menekankan bahwa kaum pencinta sesama jenis juga sama seperti manusia-manusia lainnya, sama-sama bisa berpikir, mengkreasikan sesuatu, menciptakan konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran yang cerdas, dan lain sebagainya, yang membedakan hanyalah bahwa mereka memiliki kecenderungan seksual bertolak belakang dengan manusia lainnya. Kaum gay juga memiliki sifat setia dan selalu ingin melindungi pasangannya. Sesuatu yang sudah jarang didapati dalam masyarakat heteroseksual. Berbeda dengan karakter kaum homoseksual yang umumnya memiliki orientasi utama pada pemuasan nafsu seks, Dhimas dan Ruben digambarkan sebagai sosok yang berbeda:
Novel ini mengangkat sisi minor, atau sisi yang jarang dilihat dari kaum homoseksual. Lewat teks, pengarang ingin menjungkirbalikkan anggapan-anggapan negatif masyarakat yang telah menjadi stereotip tadi. Kaum homoseksual tidak selamanya seperti yang mereka pikirkan, tetapi banyak juga dari mereka yang menjadi pemikir dan memiliki visi yang hebat di bidangnya. Bahkan tokoh-tokoh besar dunia seperti Plato, Foucault, Alexander The Great, dan Leonardo Da Vinci adalah seorang gay. Di sini pengarang mencoba menekankan bahwa kaum pencinta sesama jenis juga sama seperti manusia-manusia lainnya, sama-sama bisa berpikir, mengkreasikan sesuatu, menciptakan konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran yang cerdas, dan lain sebagainya, yang membedakan hanyalah bahwa mereka memiliki kecenderungan seksual bertolak belakang dengan manusia lainnya. Kaum gay juga memiliki sifat setia dan selalu ingin melindungi pasangannya. Sesuatu yang sudah jarang didapati dalam masyarakat heteroseksual. Berbeda dengan karakter kaum homoseksual yang umumnya memiliki orientasi utama pada pemuasan nafsu seks, Dhimas dan Ruben digambarkan sebagai sosok yang berbeda:
“Uniknya, sekalipun sudah sekian lama mereka resmi menjadi pasangan, Ruben dan Dhimas tak pernah tinggal seatap sebagaimana pasangan gay lain. Kalau ditanya, jawabannya: supaya bisa tetap kangen. Tetap dibutuhkan usaha bila ingin bertemu satu sama lain” (2001:13).
Dari kutipan tersebut bisa dilihat paradigma kedua tokoh yang mempunyai carapandangnya sendiri terhadap makna sebuah hubungan yang harmonis. Mereka menganggap bahwa hubungan yang mesra tidak hanya sekadar terekspresikan lewat hubungan seksual belaka. Hal ini berkaitan juga dengan wawasan dan kecerdasan yang dimiliki. Dhimas dan Ruben ditampilkan sebagai sosok berwawasan luas dan tergila-gila dengan ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan mereka yang tidak sembarangan. Ruben adalah seorang dokter lulusan Johns Hopkins Medical School dengan predikat cum laude. Sedangkan Dhimas mengenyam studi perguruan tingginya di George Washington University bidang ilmu sastra inggris. Hubungan mereka terjalin semenjak saling mengenal ketika menempuh studi perguruan tinggi di Washington DC. Tingkat pemikiran mereka yang di atas rata-rata tercermin dalam kutipan berikut ini:
“Dan Ruben pun masih tetap pahlawan Dhimas yang dulu. Si Indo-Yahudi bersemangat tinggi yang selalu sibuk menggabung-gabungkan ilmu psikologi dengan teori-teori kosmologi yang Cuma bisa ia mengerti sendiri. Ruben yang selalu menyebut dirinya sang psikolog kuantum. Kobaran semangatnya mampu menyalakan tungku banyak orang. Dengan ide-ide yang segar, Ruben adalah inspirator sekaligus kritikus paling sempurna buat Dhimas. Tak ada tulisan ataupun naskahnya yang tidak lebih dulu terplonco diskusi panjang dengan Ruben” (2001:12).
Lewat kutipan tersebut bisa dilihat bagaimana kualitas konsep berpikir kedua tokoh itu. Walaupun dalam hal ini tampak bahwa Ruben yang lebih dominan. Bisa kita lihat pula bahwa hubungan keduanya tidak hanya sebatas hubungan emosional, tetapi lebih dari itu, Dhimas dan Ruben masing-masing menganggap pasangannya sebagai partner hidup, tempat bertukar pikiran, tempat saling membelajarkan. Cara pandang seperti itu yang mengantarkan mereka pada sebuah cita-cita besar, yakni membuat sebuah roman masterpiece yang menghubungkan semua percabangan ilmu sains. Dengan latar belakang intelektualitas tinggi, cita-cita tersebut menjadi wajar dan masuk akal bagi keduanya. Proses penggarapan roman tersebut melahirkan tokoh-tokoh lainnya dalam novel ini. Supernova “Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh adalah cerita di dalam cerita. Pada beberapa bagian Dhimas dan Ruben berperan sebagai pencerita dalam novel.
Sigmund Freud mengatakan, para invert juga menampakkan perilaku yang berbeda-beda dalam menilai keganjilan insting seksual mereka (2003:4). Sebagian pelaku invert menganggap kecenderungan seksual atau libido yang mereka miliki adalah sesuatu yang wajar, sama halnya dengan mereka yang bukan invert, sehingga mereka menuntut perlakuan yang sama dalam lingkungan sosial. Namun, sebagian lagi bagaimanapun juga mengganggap ada yang tidak normal dengan dirinya, dan berusaha mengeluarkan diri dari karakter invert mereka. Di dalam novel ini Dhimas dan Ruben adalah pelaku invert yang mengganggap kecenderungan seksual mereka sesuatu yang wajar. Mereka samasekali tidak memusingkan apakah libido yang mereka miliki tersebut menyimpang atau tidak. Bagi mereka eksistensi seorang manusia tidak perlu dilihat dari asal-usul kecenderungan seksualnya. Sebagai manusia yang berpendidikan, mereka lebih memilih untuk sibuk mengurusi ilmu pengetahuan dan membuat sebuah karya monumental yang menggabungkan beberapa cabang ilmu sains.
Ada dua term utama dalam wacana homoseksualitas modern, berkaitan dengan tingkat keterlibatan kaum homoseks di dalam masyarakat secara umum maupun di lingkungan homoseks secara khusus, yaitu ‘closet’ (kloset) dan ‘coming out’ (keluar). Nuraini Juliastuti menjelaskan bahwa:
“Term 'kloset' digunakan sebagai metafor untuk menyatakan ruang privat atau ruang subkultur dimana seseorang dapat mendiaminya secara jujur, lengkap dengan keseluruhan identitasnya yang utuh. Sedangkan term 'coming out' digunakan untuk menyatakan ekspresi dramatis dari 'kedatangan' yang bersifat privat atau publik. Pemakaian term 'closet' dan 'coming out' disini bermakna sangat politis. Narasi 'coming out of the closet' menciptakan pemisahan antara individu-individu yang berada didalam dan diluar kloset. Kategori yang pertama diberi makna sebagai orang-orang yang menjalani hidupnya dengan kepalsuan, tidak bahagia, dan tertekan oleh posisi sosial yang diterima dari masyarakat. 'Kloset' kemudian bermakna strategi akomodasi dan pertahanan yang diproduksi untuk menghadapi norma-norma masyarakat heteroseksual di sekitarnya” (http://www.kunci.or.id/esai/nws/05/gay.htm).
Seperti dikatakan di atas, dikotomi dua term tersebut sarat dengan nuansa politis budaya heteroseksual, yang bertujuan untuk melestarikan keterpencilan dunia homoseksual dengan realitas kehidupan sehari-hari. Di dalam hal ini, ‘closet’ kemudian bermakna sebagai strategi akomodasi dan pertahanan yang diproduksi untuk menghadapi norma-norma masyarakat heteroseksual di sekitarnya (http://digilib.petra.ac.id/ads-cgi/viewer.pl/jiunkpe/s1/ikom/2006). Strategi represif yang diterapkan masyarakat heteroseksual untuk mengeluarkan homoseksual dalam kehidupan masyarakat melahirkan istilah ‘Closet Practice’. Strategi ini mulai dilakukan sejak tahun 1940-an, dan semakin intens berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an. Di dalam Supernova “Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh”, meski tidak secara langsung, sosok Dhimas digambarkan sebagai seorang homoseks yang masih berada di bawah bayang-bayang term ‘closet’ ini. Saat perkenalan pertamanya dengan Ruben, Dhimas terkesan ragu untuk mengakui kalau dirinya seorang homoseks, seperti dalam kutipan berikut:
“Ruben... katamu tadi, serotonin adalah deterjen otak?”
“Itu baru hipotesis, atau Cuma metafora. Kenapa?”
“Bisa jadi kamu benar. Kepalaku juga rasanya jernih. Aku kok jadi ingin jujur tentang sesuatu. Tentang diriku,” terdengar suara menelan ludah, “aku sebenarnya...”
“Gay?”
Dhimas terlongo. “Lho, gimana kamu bisa...?”
Ruben tertawa keras. “It was so obvious! Dari teman-teman hang out kamu, apartemen kamu yang katanya di Dupont Circle... dan kamu harus fly dulu untuk ngaku? Ha-ha-ha!”(2001:11).
Sebelum Dhimas hendak berkata jujur bahwa dirinya Gay, Ruben telah lebih dulu mengetahuinya setelah mengamati ciri-ciri dan kebiasaan yang dilakukan Dhimas. Setelah berkenalan dengan Ruben, Dhimas seolah merasa menemukan seorang teman sekaligus pahlawan yang sejati, yang memberinya kepercayaan diri sebagai seorang homoseks. Berbeda dengan Dhimas, Ruben digambarkan lebih berani menampilkan diri sebagai Gay, dijelaskan pula ia telah setahun ‘coming out’, seperti terdapat pada lanjutan kutipan tadi:
“Dhimas ikut terbahak. Merasa konyol.
“Tenang saja. Memangnya aku bukan?” Ruben berkata enteng.
Untuk kedua kalinya Dhimas terlongo. “Tidak mungkin... kamu kelihatannya sangat...”
“Sangat ‘laki? Siapa bilang jadi gay harus klemak-klemek atau ngomong pakai bahasa bencong! Gini-gini aku sudah ‘coming out’ dari setahun yang lalu. Orangtuaku juga sudah tahu. Malah mereka sudah kompak, katanya kalau sampai aku dipanggang di neraka bersama para pemburit seperti nasib Sodom dan Gomorah, mereka bakal minta ke Yahweh untuk ikut dibakar. Soalnya kalau aku dianggap produk gagal, berarti mereka juga. Hebat, ya?” (2001:11).
Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang homoseks tetap setia hidup di bawah term ‘closet’. Misalnya, mereka takut ditolak dalam lingkungan sosialnya seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan lain-lain, sehingga mereka memilih hidup dengan dunianya sendiri dan tetap merasa nyaman dengan kepura-puraannya. Hal ini disebabkan masih begitu kuatnya masyarakat heteroseksual merepresi keberadaan mereka. Selain dampak sosial banyak juga kerugian-kerugian lain, misalnya dampak ekonomi, seperti contoh ketika seorang pengusaha yang mengatakan dengan jujur kalau dirinya gay, bisa saja ia kehilangan karirnya karena lingkungan pekerjaan yang tidak bisa menerima keberadaan gay. Namun, banyak juga yang dengan berani ‘coming out’ atau menyatakan sikap sebagai seorang homoseks kepada masyarakat luas. Dengan ‘coming out’ orang lain akan tahu bahwa di tengah-tengah mereka terdapat kaum minoritas homoseksual, yang benar-benar ada, namun seperti tidak terlihat. ‘Coming out’ sendiri adalah sebuah proses, di mana seorang homoseks akan melewati tahapan-tahapan tertentu, hingga eksistensi dirinya diterima di lingkungan masyarakat. ‘Coming out’ bisa dilakukan dengan sengaja, atau bisa juga tidak. Pada kasus Dhimas, sesungguhnya secara tidak sengaja ia telah melakukan ‘coming out’ lewat kebiasaan-kebiasaan dirinya yang secara tidak sadar diamati oleh orang lain, yang membuat orang lain tahu kalau ia seorang gay, meskipun hal tersebut tidak diungkapkannya secara verbal. Berbeda dengan Ruben yang melakukan ‘coming out’ atas dasar kesengajaan atau melalui pilihan sikap dirinya.
Respon orang-orang di sekitar bisa bermacam-macam dalam menyikapi seorang homoseks yang melakukan ‘coming out’. Ada yang menanggapinya dengan bijaksana tanpa sikap negatif untuk meminggirkannya, seperti sikap keluarga Ruben saat mengetahui kalau dirinya seorang homoseks. Orangtuanya tidak merasa malu atau menyesal telah memperoleh seorang anak yang ternyata gay. Bahkan, mereka membela mati-matian keberadaan Ruben. Namun, tak jarang juga kita dapati tindakan ‘coming out’ yang ditanggapi dengan respon negatif. Seperti orangtua yang begitu mengetahui anaknya homoseks, merasa malu dan mengucilkannya dalam lingkungan keluarga, atau teman-teman yang mendadak memusuhi begitu mengetahuinya.
Label: Esai



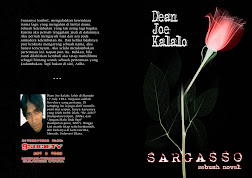


.jpg)



